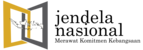Jakarta, JENDELANASIONAL.ID —– Kondisi investasi di sektor hulu migas (upstream) saat ini masih cukup memprihatinkan. Skema gross split yang diterapkan saat ini dinilai kurang menarik investor bidang eksplorasi, yang mencari cadangan migas baru. Karena itu, mesti dibuka juga skema cost recovery sehingga investor memiliki alternatif dalam berinvestasi.
“Eksplorasi itu risiko bisnisnya sangat tinggi, sehingga butuh return yang juga lebih tinggi. Karena itu skema (cost recovery) harus dibuka sebagai alternatif. Jadi investor bisa memilih,” ujar Staf Ahli Direktur Logistic Supply Chain & Infrastructur Pertamina, Rifky Effendi Hardijanto di Jakarta, Rabu (27/11).
Agar investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, maka imbal hasil (return) investasinya harus menarik. Menurutnya, dengan skema bagi hasil gross split saat ini, sulit mengharapkan investor asing masuk ke sektor hulu migas Indonesia. “Karena dengan gross split maksimum yang bisa didapat oleh investor hanya sekitar 57% gross,” ujarnya.
Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan di fiskal regim. Masalah perijinan juga perlu dipercepat. “Negara lain 4 bulan (masalah perijinan sudah selesai) sedangkan di kita bisa memakan waktu 2-3 tahun,” ujarnya.
“Harus dilihat negara-negara yang saat ini menjadi tujuan utama eksplorasi migas, bagaimana kebijakannya. Kita gak usah malu-malu belajar dari negara lain. Kita kan juga pernah jadi mentor bagi Malaysia, Mexico dll. Sekarang mereka lebih maju. Mari kita pelajari kembali dari mereka,” ujar pria yang pernah bekerja membantu Menteri Susi Pudjiastusi di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.
Padahal Indonesia pada era 1970an dan 1980an dikenal sebagai negara penghasil minyak. Sebagian besar APBN bersumber dari minyak. Saat itu, kata Rifky, produksi minyak Indonesia mencapai sekitar 1,7 juta barel. Sementara kebutuhan di dalam negeri hanya 300.000 barel. Indonesia pun menjadi negara eksportir minyak. Tetapi sejak 2004 Indonesia sudah menjadi negara importir minyak.
“Sekarang ini kebutuhanya 1,6 juta barel per hari, produksi cuma 750.000 barel sehari. Separuh harus kita impor, devisa kita hilang,” ujarnya.
Karena itu, kata Rifky, untuk meningkatkan produksi di hulu, Indonesia harus meningkatkan investasi eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak yang baru.
Menurutnya, idealnya investasi eksplorasi ini minimal US$ 8 miliar per tahun. Tetapi di Indonesia, hanya US$ 5 miliar. “Kekurangan US$ 3 miliar itu membutuhkan investasi asing. Karena untuk bermain di eksplorasi ini risikonya tinggi sekali,” ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri ESDM Arifin Tasrif tengah mempertimbangkan untuk kembali menawarkan skema pengembalian biaya operasi (cost recovery) dalam kontrak bagi hasil produksi (PSC) minyak dan gas baru. Rencananya, perubahan itu akan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
Dalam skema gross split, biaya operasional menjadi beban kontraktor. Sementara, dalam skema cost recovery, biaya operasi yang dikeluarkan operator di awal akan ditanggung oleh pemerintah.
Jika terealisasi, maka Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) nantinya dapat memilih untuk menggunakan skema kontrak yang paling nyaman, tidak harus gross split. Karena itu, dia berharap perubahan ketentuan bakal mendongkrak investasi hulu migas ke depan.
“Kami memikirkan demikian (dua skema), karena fleksibilitas itu ada, sehingga memang daya tarik untuk investasi di situ (hulu migas) lebih baik,” ujarnya seperti dikutip CNN Indonesia.com, Rabu (27/11).
Dalam Permen ESDM 52/2017 yang dirilis Menteri Ignasius Jonan, pemerintah memberlakukan skema gross split bagi kontrak baru. Namun jika kontrak bersifat perpanjangan, KKKS bisa memilih menggunakan PSC yang berlaku sebelumnya atau gross split.
Arifin mengatakan, kontraktor sangat menimbang risiko dari lapangan, di mana setiap lapangan mempunyai profil risiko yang berbeda. Dengan demikian, skema kontrak bagi hasil pada setiap lapangan pun tak bisa disamaratakan.
“Kalau gross split biasanya orang senang yang sudah pasti, kalau high risk (risiko tinggi) itu lebih yang cost recovery,” katanya. (Ryman)