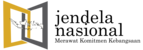Oleh: Stefi Rengkuan*)
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID – Diskusi bertema “Menulis Sejarah dan Kebudayaan Minahasa” digelar pada Sabtu, 10 Desember 2022 dari pukul 20:00 – 22:30 WITA. Topik malam ini yaitu berbicara tentang “Rincian Sistematika dan Esensi Buku Sejarah Minahasa”. Hadir sebagai pemakalah Raymond Maweikere, Yudha Tangkilisan, Bode Talumewo, Yohanes Mardam, dengan moderator Arthur Senduk dan host Roger Kembuan.
Diskusi kelompok terbatas dan terfokus tersebut merupakan kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya yang sudah memutuskan sejumlah hal antara lain sifat ilmiah penulisan yang lebih mengedepankan semacam “text book” atau isi buku dengan referensi-referensi sumber-sumber rujukan tertulis maupun lisan dan dianggap ilmiah, daripada tulisan yang biasa dibaca oleh para milenials atau anak muda kebanyakan. Hal ini disitir oleh pemakalah pertama, Raymond Maweikere, juga dipertegasnya lagi dalam sesi tanya jawab.
Dari sinilah saya berangkat dan membatasi memberi beberapa catatan, terutama akan terkait dengan aspek kebaruan (novelty) bahan materi dan pendekatan yang diangkat secara khusus oleh sejarahwan UI, Dr. Yudha Tangkilisan, MHum dan berkembang dalam diskusi.
Berbicara tentang sejarah tentu saja mengenai sebuah realitas yang sudah terjadi. Lebih spesifik lagi tentang tulisan sejarah dan segala hal yang terkait dengannya. Sejarawan hanya berusaha menggali informasi sejarah dengan prosedur tertentu untuk mendapatkan sejumlah data yang faktual dan meyakinkan dirinya dan publik pembaca.
Kita asumsikan demikian, dan tentu sambil memberi penghargaan dan ucapan terimakasih kepada para pemakalah dan para penulis dalam upaya penulisan buku (baru) tentang dan dengan Minahasa itu.
Secara singkat saya menawarkan pernyataan ini: bahwa semua pokok usulan materi penulisan baik tematis maupun kronologis ataupun campuran keduanya yang disampaikan semua pemakalah nampaknya hanya mengulangi apa yang sudah ada, dan menambahkan beberapa yang dianggap baru seperti perang Tondano, penginjilan dan pendidikan NZG Protestan dan Misi Katolik, Peristiwa Merah Putih di Manado, Permesta, dll.
Secara gamblang lagi Mner John Puah sebagai peserta penanggap pertama menyebut materi-materi lama maupun baru itu semua sekadar rentetan sejarah di Minahasa (history in Minahasa), yang dibandingkannya dengan sejarah dari dalam Minahasa (history of Minahasa).
Tentu saja semua tulisan sejarah, baik yang lama maupun yang lebih baru ditulis tentang Minahasa berusaha mengungkapkan sejarah Minahasa. Rentetan peristiwa diakronis maupun kronologis itu hanyalah suatu cara menulis secara sistematis, selain tematis. Sejatinya tulisan sejarah itu bukan tempelan atau subyektifitas maupun keterbatasan obyektif penulis sejarah. Karena itu tadi batasan kaidah ilmiah yang ketat yang telah ditetapkan tim panitia sejak awal.
Kaidah ilmiah yang dijadikan patokan itu wajib dan suatu kemestian dalam ranah ilmiah prosedur ilmiah kampus akademik. Maklumlah penggagas FGD ini adalah para intelektual bahkan akademisi kampus, yakni para dosen Unsrat dan Iluni UI Sulut. Walaupun sayang, 30 peserta yang hadir itu tergolong tidak banyak yang ikut diskusi online malam ini, untuk ukuran sebuah kampus terbesar di Sulawesi Utara dan didukung oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (terbesar di Indonesia) asal Sulut.
Tapi, hemat saya pribadi sebagai bukan alumni, grup diskusi terfokus ini melalui para pemateri dan peserta dengan bobotnya masing-masing telah sangat memperkaya dan mencerahkan, terutama keberanian mengangkat pokok-pokok baru itu. Tinggal kita lihat bagaimana dengan pokok-pokok lama, apakah masih sama isinya atau ada juga kebaruan tertentu.
Kembali ke istilah ilmiah, ditempatkan dalam kerangka menjawab tuntutan cara penulisan yang bisa menarik para milenials atau generasi muda, saya mendapat kesan bahwa ada paradoks yang tidak perlu bahkan berisi kontradiksi bila terkait dengan pertanyaan untuk apa dan siapa sejarah ditulis.

Di satu pihak tim hendak menekankan kaidah dan prosedur ilmiah. Namun di lain pihak seolah yang milenial itu tak perlu atau tak bisa dengan tulisan ilmiah. Yang milineal itu perlu dan bisa belajar dan mendalami tulisan format ilmiah. Padahal faktanya ada anak muda peminat ilmu sejarah di banyak kampus di Indonesia dan di Sulawesi Utara khususnya.
Sudah pas dikatakan bahwa usulan penulisan buku “Sejarah dan Kebudayaan Minahasa” itu formatnya adalah menurut kaidah-kaidah ilmiah yang dianut kampus atau para penulis yang dilibatkan.
Batasan ilmiah itu merupakan hal substansial dan ontologis sebuah ilmu pengetahuan sejarah seperti itu, tapi juga penting soal bagaimana itu diketahui dan dipelajari sampai dimaknai sebagai suatu seni kehidupan.
Maka perlu dilanjutkan bahwa untuk penulisan ilmiah bagi para milenial bisa dengan format ilmiah populer atau bahasa yang naratif atau dengan gambar-gambar bercerita. Atau juga melalui audio book bahkan sampai pada penggunaan teknologi metaverse, kendati tim tidak atau belum sampai ke situ.
Barangkali fakta sebenarnya adalah tim terbatas dan dibatasi. Namun tetap perlu digariswahi lagi bahwa tujuan dan relevansi penulisan sejarah ini sudah mesti memperhitungkan bagaimana itu diimplentasikan secara formal dalam bahan ajar, mulai dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi, bahkan dalam hal wacana di publik informal non formal.
Jangan sampai akhirnya buku sejarah itu kemudian hanya sampai di perpustakaan saja, apalagi hanya bisa diakses oleh segelintir ahli atau peminat belaka. Karena penulisan sejarah laiknya bukan demi penulisan sejarah itu sendiri, melainkan demi kegunaan dan memiliki tujuan bagi masyarakatnya.
Waktu terbatas untuk topik yang sangat besar ini, sehingga bisa dimaklumi apa yang dimaksud dengan esensi sejarah buku Minahasa sebagaimana menjadi bagian dari topik kurang diangkat. Pemateri nampaknya lebih fokus pada memaparkan sebanyak mungkin pokok-pokok materi, dan sedikit memberi alasan mengapa itu mesti masuk. Bahkan banyak materi yang sudah diandaikan alias otomatis mesti ada. Di sana sini sudah diberi alasan singkat khususnya terkait pokok-pokok baru yang diusulkan keempat pemakalah. Namun mesti jujur diakui memang tak semua bisa diungkap karena tentu saja uraian isinya sendiri yang akan menjawabnya. Kita lihat saja isinya nanti.
Banyak khalayak tak sabar menunggu buku itu atau draftnya diuji publik. Tapi tentu para penulis dan editor sudah tahu dan menyadari bahwa salah satu kemendesakan penulisan sejarah Minahasa adalah karena ada anggapan bahwa sejarah yang ada sekarang masih kurang diungkap. Bahkan ada yang tertulis secara keliru – kalau bukan salah – oleh pihak luar bahkan oleh sekian ahli dan publik Minahasa. Hal ini terkait siapa yang menentukan sebuah tulisan sejarah itu sahih dan siap dipublikasikan. Misalnya terkait dengan pertanyaan apakah si penulis pertama, penerbit atau instansi pemerintah, dan seterusnya.
Ambil contoh konkret terkait penulisan sejarah di zaman rezim Orba. Apakah kritik sebagian sejarawan terkait klaim kebenaran sejarah tertentu yang hilang dan kabur, bengkok dan dangkal, bahkan diputarbalikkan dan dianggap sepi oleh berbagai pihak?
Perhatikan misalnya ungkapan kesal mantan pjs Gubernur Sulut, Dr. Sonny Soemarsono sewaktu seminar tentang “Permesta dan Otonomi Daerah” di IBM ASMi, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kira-kira begini perkataannya: “Bagaimana mungkin lha wong jelas-jelas dokumen Piagam Permesta tertulis tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekali lagi tidak…eh kok malah dicap pemberontak oleh pemerintah pusat?” Nah lho”.
Pertanyaannya adalah apakah dengan memasukkan bagian ini dalam sejarah buku Sejarah Minahasa – dan sewajarnya mempertimbangkan dokumen itu – apakah stigma pemberontak bisa dicabut oleh pemerintah pusat, minimal dalam buku sejarah nasional Indonesia?
Bandingkan saja misalnya bagaimana Gus Dur berani menghapus Tap MPR RI, yaitu ketika dia memulihkan status kewarganegaraan kaum keturunan China dan kebebasannya dalam melaksanakan agama dan adat istiadat leluhur. Tentu saja Presiden KH Abdurrahman Wahid itu belajar dari ilmuwan sejarah melalui tulisan sejarah yang dianggap lebih benar (yang pernah tak dianggap) itu jua.
Kita kembali ke istilah Mner John Puah di atas. Di manakah “History of Minahasa” yang sebenarnya? Apakah hanya rentetan tulisan-tulisan lama dan baru? Di mana letak kebaruan tulisan sejarah dan kebudayaan Minahasa bila harus ditulis kembali?
Dosen senior Bahasa Jerman di Unsrat ini bertanya, mengapa tidak memperhatikan temuan-temuan terbaru, misalnya buku yang dibuat oleh Weliam Boseke berdasarkan penelitian mandiri sekian lama? Pasalnya temuan Boseke ini khususnya terkait Bahasa Minahasa sukar dibantah sampai sekarang, dan makin banyak temuannya melalui metode linguistik bandingan dalam sejarah antara bahasa Minahasa dan Han dengan memakai cara Pingyin dan cara Wade Giles (Latinisasi kaligrafi Han).

Mner Puah mau menegaskan suatu asumsi atau bahkan hipotesa ilmiah yakni salah satu kebaruan sejarah Minahasa in se -karena berangkat dari realitas berbahasa atau fenomenologi empiris bahasa yang masih dipakai masyarakat.
Barangkali bisa kita pelajari dari tesis utama temuan Boseke adalah bahwa Bahasa Minahasa hanya satu, berformat monosilabel, dan bersifat klasik atau etik (sofistikatif). Dengan begitu banyak bukti yang sudah dia tunjukkan, dan sudah ribuan pembandingan kata dan frase dalam dua bahasa itu. Ini sudah menarik dan sudah dibuktikan begitu banyak kalangan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri, termasuk para ahli dan pemakai bahasa Han. Bahkan ada beberapa tulisan lebih dahulu seperti dibuat oleh Remy Sylado, Ibu Matindas, novelis Minahasa yang juga mengindikasikan Bahasa Minahasa bahkan leluhurnya dari “negeri di atas itu”, walau tidak sedetail dan sebanyak seperti dibuat Boseke.
Dari penelusuran linguistik bandingan itulah, asal usul leluhur Minahasa menurut Boseke bisa dikisahkan yaitu berkisar sekitar abad ke-3 Masehi dalam konteks pengungsian karena perang tiga kerajaan, Sam Kok, di Tiongkok kuno, dan tiba di Tuur in tana (dalam bahasa Han: tempat tiba dengan tidak sengaja) Minahasa di Sulawesi Utara.
Pada Minggu (11/12/2022) ini diumumkan oleh Dr. Roger Kembuan sebagai host kegiatan tersebut bahwa akan ada topik khusus tentang Kebudayaan Minahasa. Tentang bahasa adalah salah satunya.
Ada ungkapan klasik, “bahasa menunjukkan bangsa”. Bahasa Minahasa menunjukkan bangsa Minahasa yang satu dan sama tentunya, yang dalam perjalanan waktu mengalami perkembangan termasuk dalam hal bahasa dalam konteks budaya dan segala aspek kehidupannya sepanjang waktu, sejak awal di tanah leluhur hingga sekarang, dan terlebih kedepan.
Kita tak bisa kembali ke zaman dahulu, termasuk dalam hal berbahasa. Yang ada sekarang mesti dipertahankan dan dikembangkan lestari terhindar dari kepunahan. Namun jelas dan terang bahwa mengenali asal usul Bahasa Minahasa itu sangat penting. Supaya kita menjadi tahu, mencintai dan diperkaya serta diperkuat dalam berkepribadian Minahasa.
Temuan Boseke adalah sebuah kebaruan dalam menggali apa yang pernah hilang. Dia meluruskan yang bengkok, menyambung yang putus, menerangi yang gelap, sekaligus menjernihkan yang kabur, serta menyingkap misteri di balik kata-kata “tua dan dolong” yang tak diketahui lagi.
Dengan demikian membangun Kebudayaan Minahasa sungguh bisa direkonstruksi sesuai kodrat asalinya. Sayang bila temuan baru dan besar ini dilewatkan begitu saja oleh para ilmuwan dan akademisi sekarang ini – untuk kemudian dikoreksi oleh generasi berikutnya. ***
*) Stefi Rengkuan adalah Presidium Riset dan Pengabdian Masyarakat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Wakil Bendahara PIKG (Perhimpunan Intelektual Kawanua Global).