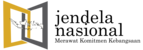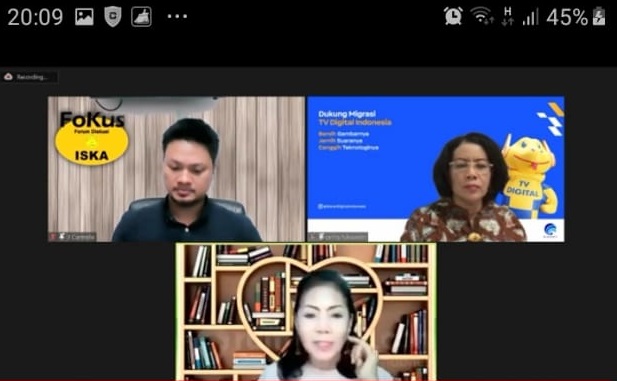Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Media sosial telah menjadi tren gaya hidup utama sejak satu dekade terakhir. Aktivitas sekitar 170 juta pengguna dengan karakteristik platform media sosial yang liberal, cepat, masif, memunculkan dualisme arus informasi yang turut menentukan identitas dan keutuhan bangsa masa depan.
Media sosial dapat menjadi lahan subur bagi benih-benih kebaikan dan narasi-narasi positif yang konstruktif seperti toleransi, kampanye nasionalisme, penggalangan bantuan bencana alam, gerakan kemanusiaan dan sejenisnya.
Namun ruang-ruang virtual tersebut juga dapat menjadi saluran penyebaran virus radikalisme, intoleransi, dan berita bohong (hoaks). Narasi-narasi ini berpotensi mengancam keutuhan dan integrasi Bangsa.

Karena itu, Fokus –Forum Diskusi—Ikatan Sarjaana Katolik Indonesia (ISKA) kembali menghadirkan diskusi bertajuk “Narasi Toleransi dalam Kanal Media Sosial” pada Jumat (9/4) pukul 19.00-20.30 WIB. Diskusi secara daring ini menghadirkan narasumber yaitu Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosita Niken Widiastuti dan Brigjen Pol. Dr. Yosepha Sri Suari.
Brigjen Sri mengawali pemaparannya dengan mengkonstruksi narasi intoleransi, radikalisme, ekstrimisme dan terorisme.
Dia mengatakan bahwa kaum intoleran, radikal sering menggunakan berita hoaks dalam menyebarkan pahamnya. Mereka sering menggunakan penafsiran agama untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak menggunakan “bahasa agama”. Karena bahasa agama itu adalah kebaikan, perdamaian dan cinta akan satu terhadap yang lain.
Mereka juga sering mempertentangkan hal yang dianggapnya sebagai sebuah “kejahatan” dan “kebaikan”, antara korban dan pahlawan. Karena itu, kaum intoleran itu selalu memandang pemerintah sebagai musuh dan melihat apa yang dilakukan pemerintah selalu salah. Karena itu, mereka mengajak para ‘calon korban’ untuk melakukan hal seperti yang dikehendakinya, dan jika mereka mengikutinya, maka akan mendapatkan imbalan ‘surga’.
Kaum intoleran dan teroris tersebut juga, katanya, menggunakan simbol berpengaruh, dan para tokoh terkenal. Ada cuplikan fakta dan jargon yang secara terus-menerus diumbar sehingga terlihat masuk akal. “Mereka mengkooptasi afeksi, mengamputasi logika, dan membagun rasa ‘kami’ dan ‘mereka’ untuk menimbulkan rasa marah yang hebat di kalangan targetnya,” ujarnya.
Saat ini, kata Sri, saat ini terjadi perang asimetris dengan skema penjajahan dunia baru. “Narasi hoaks dalam media sosial merupakan senjata yang ampuh karena media sosial itu memiliki spektrum yang luas, dan daya rusak sangat hebat, waktu yang tidak terbatas dan daya recovery yang minim,” ujarnya.
Sementara itu, Rosita Niken Widiastuti mengatakan, hoaks yang beredar diawali dengan kata sugestif dan heboh, kerap mencatut nama tokoh dan lembaga terkenal, tidak masuk akal, dan kerap disertai hasil riset palsu.
Berita hoaks juga tidak muncul di media arus utama tapi lebih banyak di aplikasi pesan instan, dan biasanya ditulis dengan huruf kapital dan tanda seru.
Diungkapkan juga bahwa bentuk hoaks yang paling banyak diterima yaitu melalui tulisan yang mencapai 62,10 persen, setelah itu gambar 37,50 persen dan video 0,4 persen.
Selanjutnya, kata Niken, saluran penyebaran hoaks yaitu melalui radio 1,20 persen, e-mail 3.10 persen, media cetak 5 persen, televisi 8.70 persen, situs web 34.90 persen, aplikasi chatting 62,80 persen dan sosial media 92,40 persen.
“Hasil survei daring Mastel yang diikuti oleh 1.116 responden pada tahun 2017 menunjukkan media sosial bahwa aplikasi komunikasi, dan situs menjadi saluran tertinggi penyeberan hoaks dalam bentuk tulisan, gambar dan video,” ujar Niken.
Dia mengatakan, pada era post-truth seperti saat ini, kebenaran, fakta dan bukti tidak terlalu penting sepanjang narasi, cerita, dan pemikiran diterima berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran dan keyakinan.
Karena itu, tumbuh subur cara-cara manipulatif dan menyihir orang untuk mempercayainya berdasarkan prinsip-prinsip di luar penalaran dan akal sehat. Masyarakat juga pada era post-truth ini adalah konsumen, produsen, sekaligus distributor informasi melalui maraknya media sosial.

Media di Era Post-truth
Pada era post truth, kata Niken, fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik karena lebih kuat emosi dan keyakinan pribadi.
Karena itu, fakta-fakta bersaing dengan hoaks dan kebohongan untuk dipercaya oleh publik.
Sebagai salah satu negara dengan pengaruh internet terbesar (keempat) dunia, Indonesia pontensial menjadi target fenomena post-truth baik untuk tujuan ekonomi maupun kepentingan politik.
Jika sebelumnya media mainstream dianggap menjadi salah satu sumber kebenaran, maka mereka harus menerima kenyataan yaitu semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi.
“Karena itu, Pemerintah berkewajiban melindungi rakyat warga negara dan kebhinnekaan bangsa dari ujaran kebencian, berita palsu dan hoax yang memecah belah masyarakat,” ujarnya.
Niken mengatakan, ASEAN telah menyepakati ASEAN SOMRI yaitu etika berinternet dengan lima nilai dalam penyebaran informasi yang disebut dengan READI, di Filipina pada 22-23 Maret 2017 lalu.
Kelima nilai tersebut yaitu responsibility atau tanggung jawab yaitu berpikir dan bertanggung jawab terhadap konten yang diunggah; Empati yakni berpikir dan berempati akan akibat konten yang diunggah terhadap perasaan orang lain; Authenticity, atau otentik yaitu tetap otentik dan siap berjaga terhadap semua konten yang diunggah; Discernment (kearifan) yakni harus kritis mengevaluasi informasi/konten online yang diperoleh sebelum mengambil tindakan terhadapnya; dan Integrity atau integritas, yakni melakukan hal yang benar, berani menyuarakan kebenaran dan melawan perilaku negatif dunia online.
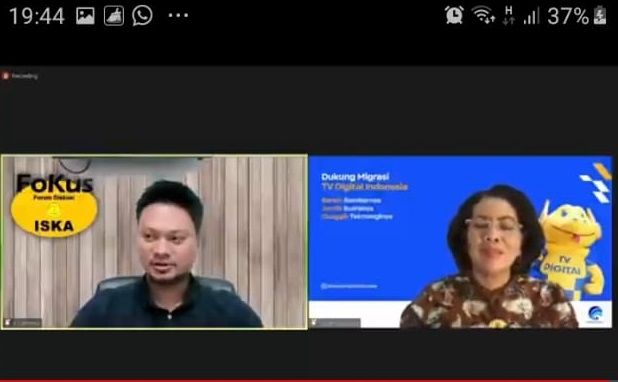
Apa yang Bisa Dilakukan ISKA
Di tengah menjamurnya berita hoaks, perilaku kaum intoleran yang semakin menguat, dan ancaman pelaku teror yang kian menggetarkan, pertanyaanya adalah apa yang bisa dilakukan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) untuk membentengi diri, masyarakat dan bangsa ini dari ancaman disiintegrasi bangsa dan menjamin tetap utuh-tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Brigjen Sri mengatakan, ISKA bisa mulai melakukan pendidikan katolik kepada keluarga-keluarga. Selain itu, juga melakukan kampanye menggunakan media sosial yang tepat bagi para kaum muda.
Dia mengatakan, penggunaan media sosial secara pribadi dapat dilakukan misalnya untuk bisa menigkatkan harga diri, memiliki prinsip, disiplin, mengenal dan mengendalikan diri, terus belajar, memperbaiki masa lalu, memperhitungkan tindakan yang diambil, komitmen dan mengenal kelebihan dan kekurangan diri.
Sedangkan penggunaan media sosial untuk kepentingan sosial misalnya bisa dilakukan untuk membuktikan cinta kasih dan perdamaian merupakan kehendak setiap agama; Mengakampanyekan Pancasila adalah ideologi terbaik bangsa Indonesia; Kebhinnekaan adalah keterberian dan Pancasila adalah roh, darah dan napas kehidupan setiap insan Indonesia.
“ISKA bisa mulai memproduksi konten digital terkait budaya nusantara, sejarah perjuangan bangsa, hubungan antar suku bangsa, pesan moral yang melegitimasi agama yang ramah, solider dan toleran, dan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Selain itu, ISKA juga bisa membentuk aliansi praktisi dan pakar dari berbagai aneka disiplin ilmu. Selanjutnya ISKA juga mulai bekerja pada semua platform media sosial, dan berjejaring dengan aliansi serupa yang sudah eksis. “Yang juga penting yaitu memberian pelayanan konsultasi, advokasi dan pendampingan dalam menghadapi persoalan ‘kehidupan’ kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Niken mengatakan bahwa berdasarkan hirarki informasi – mulai dari data, informasi, knowledge dan wisdom – kita perlu meningkatkan literasi informasi media sosial agar tidak berhenti pada informasi semata, namun bisa sampai pada sebuah kebenaran, dan kebijaksanaan.
Dia mengatakan, saat ini telah muncul gerakan “TSM” (terstruktur, sistematis dan massif) yang dimulai sejak usia dini untuk melakukan tindakan yang intoleran. “Misalnya anak-anak dilarang berteman dengan anak dari agama yang berbeda. Jadi bibit intoleransi itu sudah ditanam sejak usia dini,” kata Niken.
Diakuinya bahwa kita belum serius melakukan counter terhadap hal intoleran tersebut. Bahkan kita tidak memiliki ketahanan moral dan mental untuk menyikapi hal tersebut. Padahal, kaum intoleran itu sudah mulai menggempur semua lini, mulai dari pendidikan, sosial, politik minus kebudayaan.
Hal ini, kata Niken, harus menggugah kesadaran semua pihak untuk ikut memberi sumbangan bagi pendidikan anak secara sistematis sejak usia dini. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton saja, kita harus tergugah untuk kehidupan masa depan, rumah bersama Indonesia,” ujarnya.
ISKA, kata Niken, bisa berkontribusi di era “share informasi” ini misalnya dengan menjadi inisiator untuk melakukan konten kreatif. “Konten is the King, bagaimana kita meningkatkan konten untuk menambah kapasitas, daya tahan religius kita melalui media sosial. Sehingga kita tidak hanya menjadi penonton saja. Melalui ISKA bisa diinisiasi agar menggunakan media sosial untuk hal-hal yang membangunkan toleransi, solidaritas dan nasionalisme sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.
“Karena tujuan dari para penyebar hoaks itu menyebarkan provokasi, agitasi, mengajak orang melakukan huru-hara, memanipulasi pikiran yang pada akhirnya menimbulkan disintegrasi bangsa,” pungkasnya. (Ryman)