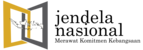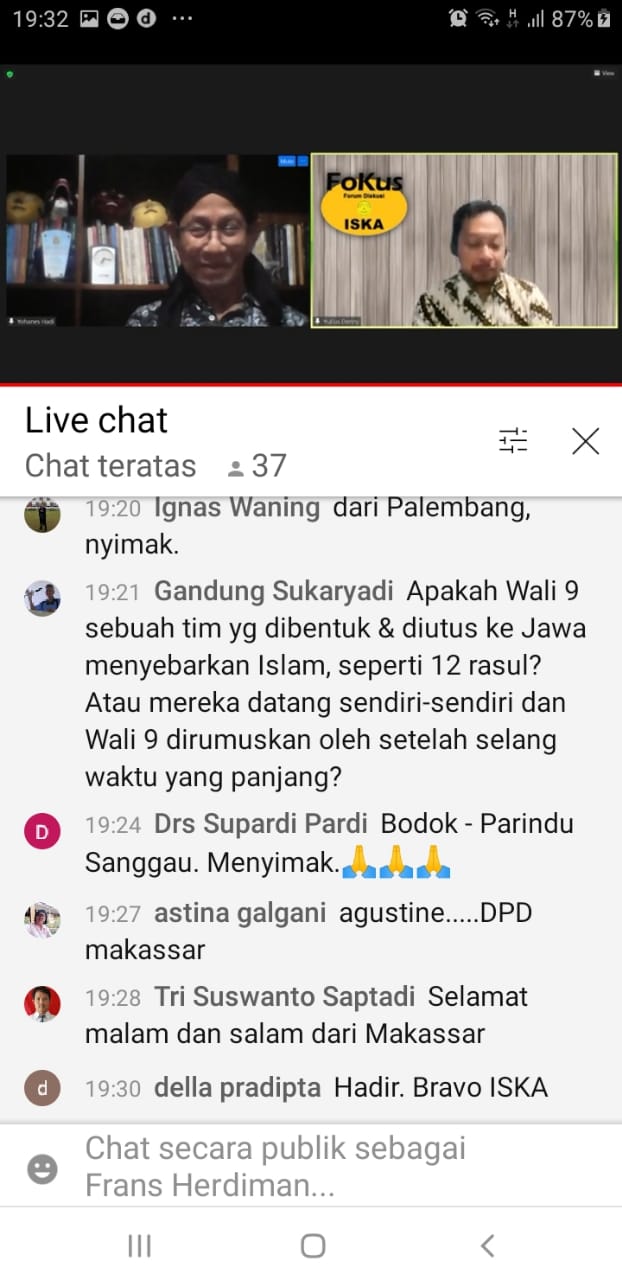Jakarta, JENDELANASIONAL.ID – Gerakan inklusivitas yang berfondasikan sikap positif, empati, tanpa memandang perbedaan, sejatinya telah tertanam kuat dalam tradisi kearifan lokal di berbagai wilayah tanah air kita sejak berabad silam.
Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keberagaman yang memahat wajah Indonesia. Sayang, praktik kearifan lokal ini belum banyak mendapat tempat di Indonesia.
Karena itu, tidak heran, jika sikap intoleransi akhir-akhir makin menyeruak. Padahal intoleransi merupakan akar dari segala tindakan radikalisme-terorisme. Dia hanya bisa dilawan dengan menebarkan sikap inklusif.
Karena itu, Fokus — Forum Diskusi — ISKA Channel seri 2, edisi 8 kali ini menghadirkan dua tokoh dari Yogyakarta yaitu Prof. Sumandiyo, Guru Besar Institut Seni Indonesia dan Romo Greg Subanar SJ, Ketua Departemen Pascasarjana Universitas Sanata Dharma yang giat menabur spirit inklusivitas dalam karya-karya mereka. Diskusi yang mengambil tema “Gerakan Inklusivitas Berbasis Kearifan Lokal” ini dilaksanakan pada Jumat, 21 Mei 2021, pukul 19.00 WIB -20.30 WIB melalui kanal Youtube ISKA Channel atau link http://s.id/fokusISKA2-8. Diskusi tersebut dipandu oleh anggota DPP ISKA, Yulius Denny.

Kearifan Lokal dan Inkulturasi
Mengawali pembicaraan Prof. Sumandiyo menjelaskan bahwa kearifan lokal itu sama dengan inkulturasi, khususnya keberadaan seni dalam ritual keagamaan.
Pemahaman seni dalam sebuah ritual agama, sangat menekankan nilai-nilai kearifan lokal, atau dapat dipahami sebagai konsep “inkulturasi” – in culture yang berarti masuk dalam sebuah kebudayaan setempat – yang berusaha untuk menumbuhkan masyarakat inklusif.
Dia mengatakan bahwa seni budaya dan agama secara empiris mempunyai hubungan yang erat, karena fenomena itu mempunyai unsur yang sama, yakni ritual dan emosional.
Ritual keagamaan merupakan transformasi simbolis dan ungkapan perasaan dari pengalaman manusia. Dan hasil akhir dari artikulasi yang sedemikian itu, merupakan emosi yang spontan dan kompleks.
Dia mencontohkan dalam sebuah ritual agama atau persekutuan doa, terkadang terasa sangat emosional ketika kita berseru: “Halelluia !” “Atau saat saya menghadiri acara Tahlilan dari saudara kita kaum Muslim, saya sangat emosional ketika ada seruan berbunyi: ‘La ilah ilalah’. Semua ini saya katakan sebagai seni ekspresif,” ujarnya.
Beberapa hasil penelitian, katanya, telah membuktikan bahwa seni pertunjukkan ternyata telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama sebagai suatu pranata pemujaan (cult institutions) yang berkaitan dengan religi, dan sebagai suatu bentuk ritual dan cara berhubungan langsung dengan dewa atau roh leluhurnya.
Dia mencontohkan pemakain topeng untuk memuji arwah atau roh leluhur yang terjadi pada saudara-saudara kita di pedalaman Dayak, Kalimantan.
“Pertunjukkan semacam ini merupakan perpanjangan aspek nilai-nilai budaya masyarakat primitif yang terus berlanjut sampai masa penyebaran Agama Hindu, Agama Islam dan Agama Nasrani, bahkan kepercayaan yang lain hingga saat ini. Jenis kesenian semacam itu dipahami dalam konsep seperti menari, menyanyi, bersenandung, dan sebagainya yang mengandung pengertian ‘manembah/menyembah’ (worship) kepada Tuhannya,” katanya.
Salah satu ritual Agama Katolik yakni korban suci seperti liturgi (Yunani: Leitourgia: Pelayanan Ibadat) yang penuh dengan tanda atau berbagai jenis simbol liturgis, bukan hanya bersifat sederhana, tetapi juga melalui perbuatan yang ekspresif dan komunikatif, sehingga dalam perkembangannya lebih sempurna ke arah sifat “karya seni.”
Suatu ritual agama, katanya, merupakan suatu pola yang cocok dari gerakan seremonial, bunyi-bunyian, dan berbagai ucapan verbal, sehingga biasa menciptakan suatu kerangka yang dapat menggantikan atau berhubungan dengan tindakan religius.
Terkait sikap agama terhadap seni, ternyata ada berbagai macam agama yang berciri ritualistik, dan bersifat perayaan pesta (orgiastic). Atau ada agama yang cendrung mengajarkan cinta kasih dan kedamaian, ternyata banyak mengembangkan berbagai macam simbol ekspresif atau seni, seperti nyanyian, musik, gerak dan bentuk seni “pictoral” lainnya.
Ritual keagamaaanya yang penuh dengan berbagai macam pembentukan simbol ekspresif-komunikatif tersebut dapat menggugah hasrat manusia.
“Kesenian tidak hanya menciptakan keindahan saja, tetapi juga meyakinkan orang pada kebenaran Kitab Suci. Seni melayani cita-cita keagamaan dengan melukiskan berbagai macam gambar keagamaan, dan terutama merupakan pernyataan kebaktian atau devosi,” katanya.

Tanpa Simbol Tak Mungkin Ada Partisipasi
Inkulturasi dipopulerkan sekitar tahun 1959 dalam Teologi Misi, yakni dari kata “in” dan “culture”, yakni “masuk ke dalam kebudayaannya.” Istilah ini semakin dikenal di lingkungan Gereja Katolik sesudah Konsili Vatikan II (Tahun 1960-an), dengan lebih menekankan bahwa warta dan pesan Kristus harus berakar dalam nilai-nilai kearifan budaya lokal.
Sesungguhnya konsep “inkulturasi” yang berusaha masuk ke dalam kebudayaan atau “in” & culture”, hakekatnya adalah berusaha untuk menumbuhkan inklusivitas, yakni melibatkan semua tipe kebudayaan atau masyarakatnya (including everything or all types of people).
Kelompok tertentu yang mempunyai niat (will) memahami cara pandang orang lain/kelompok lain, berusaha menggunakan sudut pandang orang lain dalam memahami masalah.
Dia menjelaskan bahwa salah satu contoh inkulturasi adalah perayaan selamatan di Gereja Ganjuran Yogyakarta. Setiap tahun dirayakan acara selamatan ini sebagai sebuah kearifan lokal yang dihadari oleh semua umat beragama apa pun. “Jadi acara selamatan ini bersifat inklusif,” ujarnya.
“Simbol ekspresif atau seni sebagai salah satu bahasa ungkap, nampaknya perlu hadir dalam konteks sebuah ritual keagamaan, karena dapat diketahui bahwa berbagai macam simbol seni, merupakan hakekat dari keberadaan ritual. Tanpa simbol itu, tak mungkin ada partisipasi dalam keterlibatan religiositas yang kudus dan suci. Dan simbol ekspresif atau seni diterima sebagai manifesatasi yang suci itu,” ujarnya.
Suatu ritual keagamaan yang hidup, katanya, selalu menantang untuk menemukan atau mengekspresikan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan budayanya untuk melakukan ibadat itu. Oleh karena itu, proses inkulturasi atau menyesuaikan dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal, merupakan peranan yang sangat menentukan dalam gerakan inklusivitas.
Mengakhiri pembahsan, Prof Sumandiyo mengambil sepenggal kutipan yang menarik dari Kuliah Umum Presiden Jokowi, di ISI Denpasar, pada 24 Juni 2018 yaitu, “Dibutuhkan kreativitas yang menghasilkan karya-karya seni yang mengakar pada kearifan lokal, sekaligus menjadi pondasi untuk membentuk masa depan baru. DNA kita adalah seni dan budaya. Kita memiliki 714 suku bangsa di Indonesia dengan ciri khas budaya, seni, adat dan tradisi masing-masing.”
Wajah Kekuasan di Tengah Pandemi
Sementara itu, Romo Greg Subanar menyampaikan beberapa masalah mendasar dalam menghadapi pandemi Virus Corona-19.
Dia mengatakan, selama ini, laju perkembangan peradaban berjalan di atas rel ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan. Namun tiba-tiba kita harus melakukan “rem mendadak” karena situasi Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih merajalela di seluruh Dunia.
Hal ini, katanya, merupakan kegoncangan hidup yang menimpa semua sektor kehidupan, seperti industri, ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain. “Kegoncangan hidup ini mengharuskan kita untuk mencari keseimbangan, kemudian kita harus masuk pada tahap-tahap mengatasi masalah pandemi tersebut,” ujarnya.
Dalam situasi yang demikian, katanya, kita dihadapkan bagaimana “kekuasaan” tampil untuk menentukan apakah kita sehat dan sakit.
Menurutnya, dalam kasus pandemi tersebut, ada tiga wilayah kekuasaan: wilayah sosial, wilayah kultural dan wilayah medis/klinis.
Dijelaskannya, kekuasaan dalam wilayah sosial misalnya, dia yang mengeluarkan aturan yaitu kita harus mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. “Ini merupakan kekuasaan wilayah sosial. Dengan cara ini, maka penyebaran Covid 19 dapat diatasi.” ujarnya.
Kemudian dalam wilayah kultural, misalnya dilakukan dengan berbagai promosi obat-obat tradisional dan jamu, yang katanya bisa menyembuhkan pasien Covid 19. Selain itu ada juga ritus atau upacara adat yang dilakukan di berbagai tempat, yang katanya bisa menjauhkan seseorang dari serangan Covid 19. Semua ini merupakan ekspresi yang dilaksanakan di wilayah kultural.
Terakhir, wilayah kekuasaan ketiga yakni wilayah medis yang menentukan sehat dan sakit. Dalam kekuasaan medis ini, ada kegiatan/program yang dikenal dengan istilah Swab, Rapid Test dan Vaksin. Semua ini, katanya, merupakan tindakan untuk menentukan sehat dan sakit.
“Dan kekuasaan medis/klinis ini merupakan kekuasaan yang paling dominan saat ini, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh Dunia.” ujarnya.
Menghadapi situasi seperti ini, manusia berupaya keras agar segera keluar dari gempuran pandemi Virus Corona. Karena itu, katanya, manusia mengalami keterbatasan daya usaha untuk keluar dari pandemi tersebut.
“Pasien misalnya, ingin sembuh. Tenaga kesehatan berusaha melakukan tindakan yang menyelamatkan nyawa manusia. Dan keluarga berusaha memberi dukungan kepada pasien,” ujarnya.

People of Hope
Dalam sessi tanya jawab, kedua Guru Besar tersebut seolah “melawan arus” ketika menyikapi kasus intoleransi yang semakin merajalela saat ini. Keduanya berkeyakinan bahwa kasus intoleransi akan semakin kecil karena gerakan kearifan lokal, yang merupakan basis dari gerakan inklusivitas, akan semakin besar.
“Saya yakin gerakan berbasis kearifan lokal itu, gerakan inklusivitas, akan semakin besar. Sekarang ini tren-nya bahwa semangat inklusivitas sudah semakin diterima. Kita semakin inklusif,” ujar Sumandiyo.
Sebagai seorang praktisi seni, Sumandiyo mencotohkan bahwa gerak tari, yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal, merupakan gerak bahasa universal. Semua orang, katanya, bisa menari. Karena itu, katanya, menari terbuka pada bahasa universal.
Memang harus diakui bahwa masih ada warga yang tidak menghargai kearifan lokal. Hal itu terjadi karena belum adanya keterbukaan terhadap kearifan lokal. Intoleransi itu terjadi, katanya, karena orang kurang menghargai kearifan lokal. Karena itu, kearifan lokal perlu ditanamkan melalui pendidikan.
Romo Banar mengakui bahwa banyak anak muda saat ini mengalami keterasingan dengan kearifan lokal. Karena itu, dia mengajak kaum muda untuk memiliki keterbukaan terhadap orang lain.
“Keterbukaan menjadi syarat utama. Syarat berikutnya adalah membutuhkan kerelaan waktu. Caranya yaitu terlibat, membuka diri. Hal itu tidak bisa diteorikan, hanya bisa dipraktekkan” ujarnya.
Selain itu, Romo Banar juga mengajak kaum muda untuk terlibat dan menjadi produsen, bukan hanya konsumen. Di era sosial media seperti saat ini, katanya, setiap kita diminta untuk tidak hanya menjadi follower.
Ada data bahwa saat ini kaum intoleran makin mengeras. “Dari data itu saya mengajak kita untuk mari terlibat, jangan hanya menjadi seorang follower,” ujarnya.
Karena itu, Romo Banar mengajak warga Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) untuk berpikir jernih. Dia juga meminta insan ISKA agar memilah bahasa yang di-posting melalui media sosial.
“Ada bahasa altar, ada bahasa pasar dan ada bahasa pelataran. Kita bisa menjadi kerdil ketika masuk di dalam medsos. Karena itu, jika kita tidak kritis maka kita akan bahaya dalam situasi pandemi ini,” ujarnya.
Pandemi ini, katanya, bisa membuat banyak orang menjadi frustrasi hingga depresi. Karena itu, dia mengajak agar manusia terus memiliki harapan bahwa di balik pandemi ini ada misteri salib yang harus dipikul (people of hope).
Dalam closing statement-nya, Sumandiyo kembali menegaskan bahwa gerakan inklusivitas yang berbasis pada kearifan lokal itu sangat penting, apalagi dalam seni pertunjukkan. Seni pertunjukkan bisa membantu mewujudkan gerakan inklusivitas yang berbasis kearifan lokal.
“Karena melalui bahasa seni, bahasa universal, bisa menembus perbedaaan politik, etnis, kultural. Itu sangat penting sekali,” ujarnya.
Romo Banar mengatakan bahwa situasi pandemi ini akan terus berjalan. Namun, dia berharap, tidak mematahkan semangat kita bersama dan memudarkan semangat kita mencari jalan untuk terlibat.
“Sama seperti kata-kata Yesus ketika memberi makan lima ribu orang, Yesus mengatakan kepada para muridnya ‘kamu harus memberi mereka makan’. Karena itu, kita juga harus mengatakan hal yang sama yaitu “kita harus memberi mereka makan”. Ini adalah ungkapan bahwa kita adalah ‘people of hope’,” ujarnya. (Ryman)