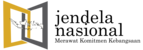Oleh: Edi Danggur, SH, MM, MH
Di tengah masyarakat kita sering ada praktek pinjam-meminjam uang oleh individu (debitur) pada bank, koperasi bahkan individu (kreditur). Bunga pinjaman biasanya variatif. Bank dan koperasi biasa menerapkan bunga yang wajar. Tetapi kalau krediturnya adalah individu, bunga pinjaman biasanya sangat tinggi.
Tingginya bunga pinjaman seringkali menyebabkan ketidakmampuan si peminjam (debitur) pada tanggal jatuh tempo untuk membayar, baik hutang pokok maupun bunga. Tidak mampu bayar hutang itu Istilah teknis hukumnya gagal bayar, ingkar janji, cidera janji atau wanprestasi.
Untuk meminimalisasi resiko debitur gagal bayar maka tanah dan bangunan si debitur dijadikan barang agunan atau jaminan. Sehingga selain menandatangani Perjanjian Pinjaman Uang, ditandatangani pula akta atau Surat Kuasa Mutlak (SKM) dari debitur kepada kreditur.
Dengan SKM itu, manakala debitur gagal bayar pada tanggal jatuh tempo maka kreditur diberi wewenang untuk menjual barang agunan guna menutup hutang pokok dan bunga. Pembelinya siapa saja yang dikehendaki kreditur, termasuk menjual kepada si kreditur sendiri.
Itu artinya ketika hutang sudah jatuh tempo dan debitur tetap gagal bayar maka barang agunan otomatis menjadi milik kreditur. Dalam praktek, tidak seperti surat kuasa lainnya, dalam SKM itu ada klausula bahwa SKM itu tidak dapat dicabut karena alasan apapun juga.
Ada tiga masalah hukum (legal issues) yang dibahas dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana hukum positif kita mengatur praktek pinjam meminjam uang dengan SKM itu? Kedua, bagaimana pandangan mayoritas hakim kita jika mereka menghadapi perkara yang menyidangkan keberatan debitur menolak SKM itu? Ketiga, apa akibat hukumnya jika ternyata dalam praktek, warga masyarakat tetap menggunakan SKM?
Penyalahgunaan Keadaan
Biasanya hanya karena kebutuhan uang yang mendesak maka debitur mau saja menandatangani SKM tersebut. Jika ada pilihan lain yang lebih menguntungkan debitur, tentu debitur tidak mau menandatangani SKM itu. Sebab, SKM itu berisi janji yang sangat berat!
Bayangkan, tanah dan bangunan yang biasanya harganya mahal, hanya dinilai sebesar hutang pokok dan bunga. Tentu sangat tidak adil bagi debitur. Sebab pelaksanaan isi SKM itu (menjual barang agunan atau dimiliki sendiri oleh kreditur) otomatis menurunkan nilai atau harga barang jaminan tersebut.
Sebenarnya UU kita sudah mengupayakan perlindungan hukum terhadap kedudukan debitur yang lemah. Untuk mencegah penyalahgunaan keadaan debitur yang lemah tersebut, Pasal 1178 KUHPerdata menegaskan: “Segala janji dengan mana si berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik, adalah batal”. Larangan demikian dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “vervalbeding”.
Larangan serupa ditegaskan pula dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan (“UUHT”): “Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, adalah batal”. Dengan hadirnya UUHT maka hipotik atas tanah dan credietverband diganti dengan Hak Tanggungan.
Tetapi dengan alasan “suka sama suka”, praktek pinjam-meminjam uang dengan SKM itu sulit dihindarkan. Seolah-olah pemerintah menutup mata terhadap akibat pelaksanaan SKM itu. Ada yang jatuh miskin karena tanah dan bangunan jatuh ke tangan kreditur dengan harga murah.
Untuk menyelamatkan warga masyarakat yang jatuh miskin akibat praktek SKM itu, maka pada tanggal 6 Maret 1982 Menter Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Instruksi No.14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan SKM Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Intruksi itu ditujukan kepada semua gubernur, bupati, walikota serta pejabat-pejabat agraria se-Indonesia.
Instruksi Mendagri tersebut berisi larangan kepada camat dan kepala desa atau pejabat yang setingkat dengan itu untuk membuat, menguatkan atau mengesahkan pembuatan SKM yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah. Demikian pula pejabat-pejabat agrarian dilarang untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan SKM sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.
Praktek Peradilan
UU sering berisi peraturan-peraturan yang bersifat umum. Maka kalau ada masalah hukum di tengah masyarakat, jangan berharap terlalu tinggi bahwa UU mampu menyediakan jawabannya. Sebab UU itu tidak luwes karena tidak menyediakan peraturan khusus untuk setiap peristiwa konkret.
Sebaliknya, putusan pengadilan sangat luwes dan mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Itu tugas hakim untuk mencari hukumnya bagi setiap peristiwa konkret dalam bentuk putusan sebagai hukum yang hidup. Maka ketika masyarakat menghadapi suatu masalah konkret, mereka langsung bertanya seperti apa praktek peradilan dalam masalah-masalah serupa.
UU memang mengatur peristiwa. Tetapi seringkali peristiwanya telah berkembang jauh sedangkan UU-nya belum juga berubah. Hukum selalu ketinggalan ketika hendak mengatur bidang ekonomi dan teknologi yang sudah melangkah jauh. Tidak heran kalau ada pemeo: “het recht hinkt achter de feiten aan”. Artinya: hukum itu selalu ketinggalan dari peristiwanya.
Bisa dimengerti karena untuk membuat UU, butuh proses yamg memakan waktu lama, bahkan bertahun-tahun. Kadang-kadang saat UU itu diterbitkan, sudah ada kemajuan baru lagi di bidang ekonomi dan teknologi yang seharusnya butuh pengaturan dengan UU.
Kekurangan UU pada umumnya diisi dengan putusan pengadilan, agar UU itu benar-benar menjawab perkembangan jaman dan kontekstual. Jika putusan pengadilan itu diulang-ulang diterapkan pada kasus-kasus serupa maka muncullah yurisprudensi. Kalau usia suatu UU semakin tua, maka semakin banyak pula yurisprudensi. Nah, bagaimana Mahkamah Agung (MA) memutuskan sengketa yang berkaitan dengan larangan janji milik beding (vervalbeding) itu?
Melalui Putusan No.3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990 (dalam kasus PT Astra International), MA menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui SKM itu tidak prosedural. Sebab pembuatan Akta PPAT ex Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 dinilai imperatif. Tidak bisa hanya dengan cara pembuatan SKM saja. Maka kreditur sebagai penerima kuasa tidak otomatis sebagai pemilik tanah yang bersangkutan. Atas dasar itu kreditur tidak dapat menuntut agar tanah yang menjadi agunan tersebut diserahkan kepadanya.
Demikian pula melalui Putusan No.3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993, MA telah melarang penjualan barang agunan oleh kreditur manakala debitur ingkar janji atau wanprestasi. Alasannya, status tanah yang semula menjadi barang jaminan, tetapi dengan klausula MILIK BEDING dalam SKM, barang jaminan menjadi milik kreditur bila debitur gagal bayar. Hal demikian bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum [Ali Boediarto, 2000:171-177).
Dengan Putusan No. 3332 K/Pdt/1994 tanggal 18 Desember 1997, MA menegaskan pula bahwa SKM itu tidak dapat diajukan sebagai bukti di persidangan pengadilan tentang adanya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Sebab hal itu bertentangan dan dilarang oleh Instruksi Mendagri No. 14/1982 yang telah diperkuat oleh Yurisprudensi MA bahwa SKM itu mengandung “perkosaan” hak penjual yang lemah ekonominya dan tidak adanya kebebasan berkontrak. Perbuatan jual beli tanah harus bersandar pada PP No. 10/1961 dan bukan melalui SKM (Ali Boediarto, 2005:15).
Batal Demi Hukum
Ketegasan MA melarang penggunaan SKM sebagai dasar peralihan ha katas tanah diikuti dengan putusan MA lainnya bahwa secara hukum SKM itu batal demi hukum (null and void). Artinya, sejak semula SKM itu dianggap tidak pernah ada.
Pendirian MA tersebut dapat dilihat dalam Putusan No.1991 K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996. MA beralasan bahwa SKM itu isinya tidak adil, dimana debitur selaku pemilik tanah menjual tanah miliknya kepada kepada kreditur dengan harga hanya sebesar hutangnya debitur yang belum dibayar. Kreditur kemudian menjual lagi tanah itu kepada pihak ketiga dengan harga sangat mahal dan sertifikat dibaliknama atas nama pembeli.
Selain itu, MA beralasan bahwa jual beli tanah dengan menggunakan SKM bertentangan dengan dengan Instruksi Mendagri No. 14/1982 dan Pasal 1320 butir ke-4 KUHPerdata, sehingga perbuatan hukum jual beli tanah tersebut batal demi hukum. Dengan batal demi hukumnya jual beli tanah melalui SKM tersebut, maka hubungan hukum yang terjadi dalam kasus di atas adalah berupa hubungan hukum hutang piutang uang dengan tanah sebagai agunannya tetap berlaku” (Ali Boediarto, 2005: 14-15].
Penegasan MA itu dapat dipahami sebab sesuai ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah sebuah perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan.
Sebagai sebuah perjanjian, surat kuasa terikat pada empat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1) adanya kesepakatan di antara mereka yang mengikatkan dirinya; (2) mereka itu mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) adanya suatu pokok persoalan tertentu yang menjadi inti perjanjian; dan (4) adanya suatu causa atau sebab yang tidak terlarang.
Apa yang dimaksudkan dengan causa atau sebab yang terlarang itu? Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan: suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Terbukti SKM itu bertentangan dengan hukum (Pasal 1178 BW, Pasal 12 UUHT dan lain-lain) artinya ada causa atau sebab terlarang, yang menyebabkan SKM itu batal demi hukum.
Mungkinkah ada alasan pemaaf bagi kreditur pemegang SKM karena tidak semua warga masyarakat tahu ada larangan penggunaan SKM dalam perjanjian pinjam meminjam uang? Tidak bisa! Sebab ada adagium universal: “nemo ius ignorare consetur” (semua orang dianggap tahu akan semua hukum atau undang-undang. Akibatnya berlaku pula adagium ini: “ignorantia legis excusat neminem” (ketidaktahuan akan hukum atau undang-undang tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf).
Penulis adalah Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta