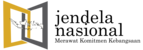Oleh: Edi Danggur, S.H., M.M., M.H.*)
SAAT ini polemik revisi UU KPK sedang panas. Dalam sidang paripurna tanggal 17 September 2019 DPR RI sudah mensahkan hasil revisi UU KPK. Itu artinya baik secara politik maupun hukum, hasil revisi UU KPK itu sah. Pasca pengesahan UU KPK hasil revisi itu, muncul persepsi yang bertolak belakang. DPR RI dan Presiden berpersepsi bahwa revisi itu bakal menguatkan KPK. Mahasiswa justru punya persepsi sebaliknya bahwa revisi UU KPK itu bertujuan melemahkan KPK. Mahasiswa pun turun ke jalan berunjuk rasa menolak hasil revisi UU KPK tersebut pada tanggal 23-24 September 2019.
Di tengah unjuk rasa yang anarkis itu muncul ide dari beberapa tokoh masyarakat agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Beberapa tokoh masyarakat pun diundang Presiden Jokowi ke istana pada Kamis 26 September 2019. Menurut Moh Mahfud MD, Perppu itu isinya adalah UU KPK hasil revisi dinyatakan tidak berlaku sampai waktu tertentu untuk dibicarakan lebih lanjut.
Ada dua masalah hukum atau legal issue di sini. Pertama, apakah ada kondisi objektif, kini dan di sini, yang memenuhi syarat untuk dapat diterbitkannya Perppu tersebut? Kedua, apakah ada solusi lain yang lebih konstitusional untuk memecahkan masalah perbedaan persepsi (melemahkan di satu pihak dan menguatkan di pihak yang lain) terkait pengesahan UU KPK hasil revisi tersebut?
Syarat Penerbitan Perppu
Secara formal konstitusional Presiden Jokowi dapat saja menerbitkan Perppu. Sebab, kewenangan Jokowi ada dasarnya dalam konstitusi. Tetapi persoalannya apakah ada syarat substantif yang terpenuhi untuk menerbitkan Perppu tersebut. Syarat substantif dimaksud, ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Makna dari pasal ini adalah adanya “kegentingan yang memaksa” sebagai syarat untuk dapat diterbitkannya Perppu.
Apakah yang dimaksudkan dengan “kegentingan yang memaksa”? Biasanya kalau orang ingin tahu tafsiran atau pengertian yang tepat dari terminologi “kegentingan yang memaksa” itu, orang mencarinya dalam penjelasan atau pengertian yang tercantum dalam konstitusi itu sendiri. Itu yang disebut tafsiran otentik atau tafsiran resmi (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2012:11). Sayangnya, konstitusi dasar kita, yaitu UUD 1945, tidak menyediakan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan kegentingan yang memaksa yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) tersebut.
Namun dalam hukum ada yang disebut tafsiran sistematis. Tafsiran demikian berangkat dari suatu pemahaman bahwa hukum itu sebuah sistem, dimana satu pasal selalu berhubungan dengan pasal lainnya, dan undang-undang yang satu saling berhubungan pula dengan undang-undang lainnya (Sudikno Mertokusumo, 2014:222). Demikian pula pasal-pasal dalam UUD 1945 itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara para pasal yang satu dengan pasal lainnya.
Oleh karena itu, Satya Arinanto, guru besar Hukum Tata Negara FH UI, mencoba menghubungkan pengertian “kegentingan yang memaksa” itu dengan pengertian “keadaan bahaya” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUD 1945: “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Lagi-lagi UUD 1945 tidak menyediakan tafsiran otentik atas terminologi “keadaan bahaya” itu (Kompas.com, 16 Oktober 2017). Seperti apa kondisi objektifnya sehingga negara dikualifikasi berada dalam keadaan bahaya, tidak dijelaskan secara memadai dalam UUD 1945.
Tetapi lagi-lagi dengan menggunakan tafsiran sistematis, kita bisa melangkah dan mencari pengertian keadaan bahaya itu ke Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) [biasa juga disingkat: ICCPR”] yang diundang-undangkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 28 Oktober 2005. Pada Pasal 4 ICCPR, keadaan bahaya didefinisikan sebagai: “menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial”.
Menurut ICCPR, keadaan darurat umum yang merupakan padanan dari “keadaan bahaya” dalam UUD 1945 mensyaratkan adanya keadaan yang mengancam kehidupan negara, keadaan itu diumumkan secara resmi, negara dapat mengambil tindakan yang menyimpang, asalkan tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi. Kondisi objektif di negara kita, kini dan di sini, tentu saja tidak sedang dalam keadaan darurat umum dimaksud.
Selain konstitusi dan undang-undang, praktek peradilan berupa putusan pengadilan atau putusan Mahkamah Konstitusi dapat juga dipakai sebagai sumber hukum untuk menemukan jawaban atas persoalan-persoalan konkret dalam masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksudkan dengan terminologi kegentingan yang memaksa, keadaan bahaya, atau keadaan darurat umum, tetapi langsung memberikan syarat-syarat dapat diterbitkannya suatu Perppu. Pada halaman 19 Putusannya itu, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
“[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila: (1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan (3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan”.
Dari ketiga syarat penerbitan Perppu itu, jika dikaitkan dengan penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak ada kondisi faktual dimana kita perlu undang-undang baru. Sebab, kita sudah mempunyai UU KPK dan kini UU KPK itu sudah direvisi yang disahkan pada tanggal 17 September 2019. Tidak terbukti bahwa negara kita mengalami kekosongan hukum, bahkan sudah mempunyai UU yang sangat memadai. Jadi, terbukti tidak ada urgensinya bagi Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu.
Maka dapat dimengerti kalau Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya bersama parpol koalisi “siap pasang badan” mendukung Presiden RI Joko Widodo di tengah polemik revisi UU KPK termasuk demonstrasi anarkis yang menolak pengesahaan atas revisi UU KPK tersebut. Hasto beralasan, revisi UU KPK sejalan dengan hasil survey bahwa lebih dari 64 persen responden setuju terhadap pentingnya Dewan Pengawas KPK sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan oleh KPK dapat dihindari (Indopos.co.id., Sabtu 28 September 2019).
Mengingat tidak terpenuhinya syarat-syarat substantif untuk menerbitkan Perppu maka saran menerbitkan Perppu dapat dianggap sebagai jebakan terhadap Presiden Jokowi. Presiden akan dianggap bertindak sewenang-wenang, menyalahgunakan kewenangannya, karena menerbitkan Perppu tanpa dukungan kondisi objektif dan memadai di dalam negeri. Penerbitan Perppu pun dapat menjadi preseden buruk di masa depan dimana setiap kali ada kelompok tertentu di dalam masyarakat tidak menyetujui kehadiran undang-undang baru atau tidak menyetujui hasil revisi atas sebuah undang-undang maka massa dikerahkan untuk unjuk rasa, lalu ada kelompok lain yang mendesak Presiden untuk menerbitkan Perppu.
Uji Materi ke MK Sebagai Cara Konstitusional
Unjuk rasa sebagai wujud kebebasan berekspresi memang diakui sebagai hak konstitusional, karena hak itu dijamin dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Hak mengeluarkan pendapat itu diatur lebih detail dalam Pasal 14 TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, Pasal 25 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahkan ada undang-undang khusus yaitu UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Kebebasan berekspresi itu pun merupakan hak universal karena hak itu dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 19 DUHAM yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah”. Demikian pula dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR menetapkan: “Hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat”.
Dalam mewujudkan kebebasan berekspresi tersebut, tentu saja ada pertarungan persepsi. Dalam konteks berlakunya UU KPK hasil revisi, mahasiswa berunjuk rasa guna menyampaikan persepsinya bahwa hasil revisi UU KPK itu bakal melemahkan institusi KPK. Sedangkan Presiden dan DPR RI mempunyai persepsi bahwa UU KPK hasil revisi itu justru bakal menguatkan kedudukan institusi KPK itu. Pertarungan kepentingan pun sulit dihindari akibat perbedaan persepsi tersebut. Mahasiswa mempunyai kepentingan agar UU KPK hasil revisi itu dibatalkan, sebaliknya DPR RI dan Presiden Jokowi bersikukuh tetap mempertahankan keberadaan UU KPK hasil revisi, termasuk menolak diterbitkannya Perppu pembatalan UU KPK hasil revisi dimaksud.
Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan DPR RI saat ini memang sungguh sangat dilematis seperti dialami Julius Caesar, pahlawan penakluk, yang tidak pernah kehilangan rasa percaya diri dan senantiasa menunjukkan kehormatan diri yang tidak tergoyahkan dalam memperjuangkan kejayaan Imperium Romawi: “Bergerak maju dapat berarti siap menghadapi peperangan (baca: unjuk rasa mahasiswa) tetapi mundur (baca: menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi) adalah sesuatu yang tidak terpikirkan. Alea iacta est! Dadu sudah dibuang, keputusan sudah diambil, tidak dapat ditarik kembali” (Michael Kerrigan, 2011:16).
Sayangnya tuntutan pembatalan UU KPK hasil revisi justru dilakukan para mahasiswa melalui unjuk rasa yang anarkis. Itu jelas tindakan inkonstitusional, tidak adil dan melanggar hukum. Jika unjuk rasa mahasiswa tersebut bertujuan mendapatkan keadilan melalui undang-undang yang secara substansi mempromosikan keadilan maka gunakan cara-cara yang baik dan adil serta tidak melanggar hukum. Sebab keadilan tidak mungkin lahir dari suatu kesalahan prosedur atau tatacara yang salah. Jangan menuntut keadilan dengan unjuk rasa anarkis, bakar-membakar fasilitas umum. Jangan pula menuntut keadilan dengan cara menyarankan pejabat publik, dalam hal ini Presiden untuk menyalahgunakan wewenangnya melalui penerbitan Perppu. Sebab seperti kata Henry Campbell Black, “nabi” para ahli hukum: “ius ex injuria non oritur” atau “a right does (or can) not rise out of a wrong” (1990:859).
Penulis juga mengkritisi pemahaman mahasiswa saat berdebat dengan Menteri Hukum dan HAM di acara ILC TV One Selasa (24 September 2019). Dikatakan seorang wakil mahasiswa: “Apakah mungkin mahasiswa yang jumlahnya begitu banyak turun ke jalan berunjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi itu tidak benar? Atau justru pemerintah yang tidak benar?” Tentu saja itu pemahaman yang salah karena mahasiswa mengukur kebenaran itu dari banyaknya jumlah mahasiswa yang turun ke jalan. Leibniz, seorang filsuf yang muncul di zaman modern mengatakan: “barangsiapa mencari kebenaran, janganlah menghitung suara”. Pernyataannya ini memiliki makna yang mendalam. Baginya kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak bisa dikompromikan berdasarkan kepentingan, tidak bisa dikalahkan berdasarkan mekanisme voting dan kebenaran juga tidak bisa dikonversikan demi keuntungan (Pius Pandor, 2014:35). Dalam konteks penolakan UU KPK hasil revisi, janganlah mengukur kebenaran dari banyaknya mahasiswa yang berunjukrasa, tetapi kebenaran harus diukur dari kesesuaian antara apa yang kita pikirkan atau katakan dengan kenyataan atau apa yang sungguh-sungguh terjadi. Bukan yang banyak otomatis benar, sebaliknya yang sedikit jumlahnya pasti salah.
Lalu, apa yang seharusnya dilakukan para mahasiswa sebagai komunitas intelektual? Seyogyanya mahasiswa menggunakan kemampuan dan kompetensinya di bidang keilmuan untuk mengajukan uji materi (judicial reiew) atas UU KPK hasil revisi tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI (“MK”). Sebab konstitusi kita sudah memberikan kewenangan kepada MK sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of constitution) untuk menyatakan apakah materi pasal-pasal, ayat-ayat dan/atau bagian UU KPK termasuk keseluruhan hasil revisi UU KPK itu mempunyai kekuatan mengikat atau tidak, atau justru MK akan memutuskan tidak mengikat (not legally binding) semua pasal hasil revisi UU KPK tersebut karena bertentangan dengan spirit, roh dan semangat UUD 1945.
Dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan, kita hasil menerima hasil akhir dari perjuangan itu, apa pun itu: menang atau kalah. Sebab seperti kata Scaliger, “humana vita est alea, in qua vincere tam fortuitum quam necesse perdere”- perjuangan dalam hidup manusia itu seperti permainan dadu, dimana kemenangan hanya menjadi sebuah kebetulan, tetapi kekalahan itu sebuah kepastian (B.J. Marwoto & H. Witdarmono, 2006:111). Namun demikian, kita tidak hanya terikat pada seperti apa hasil akhir dari permohonan uji materi ke MK yang menjadi tujuan kita, apakah kalah atau menang. Tetapi kita juga harus berusaha mencapai tujuan yang baik dan benar itu melalui cara-cara yang baik dan benar pula. Finis non iustificat medium!
*) Penulis adalah seorang advokat, tinggal di Jakarta.