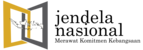Alexander Yopi *)
Saya mulai dengan Communio untuk menanggapi Pesparani Umat Katolik yang terjadi di Ambon pada 26 Oktober hingga 02 November mendatang. Communio mendasari persekutuan umat Katolik. Mereka datang dari berbagai gereja di seantero Nusantara, dari segala suku, budaya, dan bahasa. Jumlah mereka 8.000 peserta dari 34 Provinsi. Karena imannya akan Kristus yang wafat dan bangkit, mereka disatukan dalam misteri keselamatan, sebagai satu tubuh, yaitu Bapa sebagai kepala, Kristus Sang Sulung, dan yang lain adalah ranting-rantingNya.
Oleh bangunan rohani ini, peristiwa kultis yang dirayakan dalam sakramen ekaristi – yang secara liturgis terdiri atas doa, nyanyian, dan gestikulasi – adalah sebuah tanda riil, tempat perjumpaan paling hakiki, personal, dan eskatologis terhadap hidup dan keselamatan.
Tidak ada tanda dan rahmat yang lebih besar dan agung selain Sakramen Maha Kudus, yang tengah berziarah dari Golgota, menyusuri setiap individu, keluarga, dan komunitas, untuk dibawa kepada pangkuan Sang Bapa.
Dalam hal ini, perayaan kultis adalah upaya meletakkan tubuh ragawi kepada tubuh rohaniah, membantu setiap individu untuk berpartisipasi secara aktif, lalu menjawab panggilan golgota dalam setiap napak tilasnya.
Di Ambon, dalam konteks nasional, communio itu menjadi universal. Gereja lokal yang telah lama berdiri sendiri, dan hanya disatukan oleh pertemuan-pertemuan hierarkis, kini dikembalikan pada arti yang sesungguhnya, yaitu satu tubuh. Umat Allah yang berziarah menuju rumah Bapa tersebut berkumpul dan menyatakan karunianya dalam pelbagai cara dan kehendak.
Inilah awal mula, yang pertama, dan diharapkan selanjutnya menebus batas-batas untuk terpanggil membenahi persekutuan yang lama ditinggalkan. Karena hanya dalam ikatan yang hidup, yang ditandai oleh komunikasi yang dinamis, gereja dalam persekutuannya merayakan juga imannya yang kontekstual.
Melawan Diam
Kristus tak pernah berdiam diri. Dia selalu menyatakan diri dalam ruang hidup. Tiga hari merupakan waktu yang cukup untuk mengerti tentang kegelapan. Cerita selanjutnya adalah kebangkitan dan kembali pada ziarah manusia, pada perjalanan, entah di Galilea atau di Emaus.
Berdiam diri bisa sama artinya juga dengan statis. Tidak ingin bergerak. Merasa nyaman. Dalam posisi ini, sangat gampang seseorang untuk dicobai dan jatuh dalam percobaan. Seperti peristiwa Kemah Tabor, yang membuat Petrus, Yakobus, dan Yohanes merasa nyaman dan tak ingin menuruni bukit. Padahal, tugas utama adalah turun ke bukit dan berada di jalan utama, pada khalayak. Juga terhadap Kristus, yang menarik diri dari pusat kehidupan, dan dicobai tiga kali: harta, kekuasaan, dan kemuliaan. Namun, Dia akhirnya pulang pada ziarah golgota.
Di Ambon, ada gerak turun yang luar biasa dari singgasana emas yang membuat umat Katolik Indonesia merasa nyaman. Melawan diam, karena selama ini umat Katolik bersembunyi, tidak menampakkan muka, merasa nyaman, dan terkubur dalam berbagai perebutan harta, kekuasaan, dan kemuliaan di lingkungan internal gereja.
Seorang umat dari satu paroki dan paroki lain mengeluhkan tentang semangat duniawi yang sedang menggerogoti spirit pelayanan di gereja. Orang-orang yang diberi kepercayaan, menggunakan kepercayaan itu untuk memupuk kekuasaan pribadi, kelompok, dan golongannya. Orang-orang yang diurapi oleh tugas khusus merasa mendapat kemuliaan untuk menimpakan upeti, sanksi, dan hukuman kepada yang lain.
Sementara pada tataran nasional, gereja Katolik seperti menara babel, yang sibuk dengan bahasanya sendiri, dan tidak ingin memahami bahasa-bahasa yang digunakan sesamanya yang lain. Gereja Katolik merasa mampu dan seolah-olah merasa cukup untuk mampu bertahan di atas menara. Sementara sesamanya yang lain telah bercengkrama dalam persekutuan yang erat, menggalang hubungan yang saling menguntungkan, dengan kewajiban-kewajiban yang dibayar lunas baik kepada kaisar dan kepada Tuhan.
Dalam konteks ini, saya selalu berharap, Pesparani Umat Katolik, pertama-tama ialah ziarah umat beriman yang menuruni Kemah Tabor untuk menyatakan dirinya secara terang-terangan, bahwa kita ada, kita berkontribusi, dan kita berkepentingan (juga). Pertama, terhadap kontestasi dan proses politik nasional yang akhir-akhir ini diambil alih untuk kekuatan ziarah umat manusia di jalan negara, jalan umum para khalayak. Kedua, terhadap alokasi anggaran yang berimbang dan kesadaran umat Katolik untuk menggunakan berbagai fasilitas secara adil dan jujur. Ketiga, terhadap kebijakan, yang tentu saja harus jelas distingsinya, antara halal bagi semua golongan, tetapi tidak dengan cara menghalalkan segala cara.
Di lain pihak, gereja yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, kini saling bertemu dan memperjuangkan egonya. Dari pertemuan ini, mudah-mudahan ada pergeseran kesadaran bahwa ego bukanlah jawaban yang tepat untuk persekutuan. Karena ego menguburkan talenta dan menghimpit karunia menjadi tidak berkembang. Ego jugalah yang membuang benih-benih persekutuan yang baik di semak belukar atau di jalan raya.
Perlombaan itu dapat menjadi etalase dari buah persekutuan yang baik dan gereja-gereja lokal dapat kembali kepada jati dirinya sebagai murid, selalu ingin belajar seperti kedua belas murid, bahkan dengan cara yang paling pedas, mendapat kecaman Sang Guru karena disebut munafik.
Perayaan Liturgis
Kita kembali pada liturgi, pada lagu-lagu gereja Katolik. Inilah perayaan yang salah satunya menjadi ciri khas dan identitas yang berbeda dari gereja-gereja lainnya. Kendati dalam setiap gereja lokal, ada perbedaan-perbedaan kecil karena adaptasi lokal terhadap budaya, tradisi, dan bahasa, namun perayaan liturgi adalah harta kekayaan tak ternilai yang bersumber dari iman dan penghormatan mendalam terhadap Sakramen Maha Kudus.
Pertanyaannya adalah ke manakah kiblat perayaan kultis (saat) ini? Para pakar liturgi mungkin punya jawaban yang sama. Tetapi, jawaban itu belum tentu sama untuk umat Katolik dewasa ini. Bisa dipahami, tetapi (berharap) jangan sampai dimaklumi. Karena jawaban-jawaban yang berbeda itu lahir dari upaya tanpa sadar, tanpa sengaja, atau tak mau tahu terhadap fenomena mengadopsi atau mencampur aduk tanpa ada distingsi yang jelas antara yang liturgis dan yang profan, yang wajib dan yang fakultatif, yang Katolik dan yang bukan Katolik.
Fakta lain, bahwa harta kekayaan tak ternilai seperti lagu-lagu Gregorian dan Polifoni Suci pada zaman renainsans mulai ditinggalkan. Dalam dimensi penyembahan, lagu-lagu itu berkarakter nafas panjang, harmonis, dan bermawas diri. Kita tidak mungkin akan berteriak diiringi dengan musik sensasional untuk lagu-lagu ini. Kita juga tidak mungkin mengandalkan hanya satu orang dan yang lain berdiam diri. Karena lagu-lagu ini menghendaki komunitas bernyanyi bersama, bergantian, sambung menyambung.
Inilah juga wajah liturgi kita saat ini. Minim komposer dan konduktor. Komposer yang memahami arti liturgi yang sesungguhnya, yang tidak hanya sekedar meletakkan notasi sesuai dengan selera zaman. Lalu konduktor, yang memilih dan memimpin lagu-lagu pujian dan penyembahan tersebut sesuai dengan nafas Katolik.
Mudah-mudahan Pesparani ini menjadi gerak turun untuk mencermati betapa nyamannya gereja berada di bubungan Bait Allah, dilarikan roh jahat untuk menjauh dari Sakramen Maha Kudus. Kita bahkan mungkin tidak menyadari sedang bernyanyi di atas bubungan Bait Allah dan bukan di hadapan Sakramen Maha Kudus, karena terlena oleh kekuasaan dan kemuliaan yang ditawarkan roh jahat.
Pesparani, baiklah menjadi komposer dan konduktor bagi kita untuk kembali pada kiblat dan jati diri yang benar-benar Katolik.
Penulis adalah alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero (STFK), Kampus Ritapiret