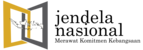Oleh : Wartika*)
Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Indonesia kembali akan menggelar Pilkada di tahun depan, tepatnya pada 23 September 2020, masyarakat di 270 daerah dengan perincian 9 provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, ditambah masyarakat di 224 kabupaten dan 37 kota akan diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerahnya yang baru atau masih percaya kepada incumbent atau petahana. Ancaman penggunaan politik identitas terus menjadi momok politik (political spectre) yang patut dicermati dan didalami oleh pemangku kepentingan yang berwenang, karena politik identitas akan memicu terjadinya polarisasi masyarakat khususnya sebelum, selama bahkan pasca pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Sinyal-sinyal awal akan munculnya politik identitas mulai tercium di beberapa daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 seperti misalnya di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Salah seorang Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan/KKSS Kabupaten Sorong Selatan mengkhawatirkan penggunaan politik identitas dalam Pilkada 2020 tersebut. Indikasi awalnya adalah adanya pembentuk lembaga masyarakat adat atau LMA yang dinamakan LMA Tehit yang telah menginisiasi terbentuknya Kelompok Tehit Bersatu demi kepentingan politik para Bakal Calon Bupati Sorong Selatan yang berasal dari Suku Tehit.
“Pembentukan kelompok tersebut tentu menciptakan kelompok kesukuan dan membentuk jarak dalam kehidupan sosial masyarakat berdasar identitas kesukuan. Menguatnya identitas kesukuan menjelang Pilkada 2020 akan menimbulkan kerawanan terjadinya konflik horizontal jika Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang didukung kalah,” ujarnya seraya menambahkan hingga saat ini, Suku Nusantara, Suku Imekko dan Suku Maybrat belum membuat kelompok tandingan. Namun, Paslon Bupati dan Wakil Bupati diperkirakan akan membentuk kelompok kesukuan sebagai langkah upaya mengamankan dukungan suara.
Menurut sejumlah sumber di Kabupaten Sorong Selatan, kelompok Tehit Bersatu diinisasi oleh Pieter Kondjol, Alfons Sesa, Yunus Saflembolo dan Martinus Salamuk sebagai upaya untuk mengalihkan dukungan masyarakat Suku Tehit dari Samsudin Anggiluli yang juga merupakan petahana.
Politik Identitas : Binatang Apakah?
Pembentukan identitas dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. Hal inilah yang akan melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, sosial itu sendiri dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial. Proses terjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya (Sukamto, 2010:13 dalam Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi “Lokalitas dan Globalisasi” yang diterbitkan dalam Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang. Vol.2). Sedangkan adanya politik identitas etnisitas juga secara langsung atau tidak langsung, nyata atau tersamar melahirkan perubahan sosial.
Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas agama dan etnis. Hal ini dapat dilihat pada keikutsertaan partai-partai politik yang mengikuti pemilu atau pilkada sebelumnya. Proses demokrasi khususnya dalam Pilkada saja seringkali tidak terlepas dari peran serta beragam partai dengan berbagai ideologi yang ikut merongrong. Berbagai ragam identitas agama dan etnis sering kali dijadikan alat politik. Penguatan identitas politik dan representasi politik secara otomatis muncul sebagai dampak dibukannya kran partisipasi politik yang dimulai sejak era refomasi hingga sekarang (Ana sabhana dan Suryani, 2016:21 dalam bukunya berjudul Politik Identitas dan Nasionalisme Kebangsaan, Jakarta:LP2M Uin Syarif Hidayatullah).
Secara teoritis, politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas merupakan tidakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula dari upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.
Sedangkan Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis (Cressida Heyes, 2007 dalam bukunya berjudul Identity Politic. Amerika Serikat: Stanford Encyclopedia of Philosophy). Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati politik identitas biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. (Hellner, 1994:4). Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama.
Dalam perjalanan berikutnya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas untuk memapankan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.
Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16 dalam bukunya berjudul Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan Indonesiatera). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bias dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.
Jadi secara umum teori umum politik identitas dan berbagai hasil penelitian menunjukkan, ada dua faktor pokok yang membuat etnis dan agama menjadi menarik dan muncul (salient) untuk dipakai dan berpengaruh dalam proses politik. Pertama, ketika etnis dan agama menjadi faktor yang dipertaruhkan. Ada semacam keperluan untuk mempertahankan atau membela identitas yang dimiliki suatu kelompok. Kedua, ketika proses politik tersebut berlangsung secara kompetitif. Artinya, proses politik itu menyebabkan kelompok-kelompok identitas saling berhadapan dan tidak ada yang dominan, sehingga tidak begitu jelas siapa yang akan menjadi pemenang sejak jauh-jauh hari. Pemilihan umum, termasuk Pilkada, adalah proses politik di mana berbagai faktor seperti identitas menjadi pertaruhan. Tinggal sekarang bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalamnya mengelola isu-isu seperti etnis dan agama, menjadi hal yang masuk pertaruhan.
Menurut Nuri Suseno dalam bukunya yang berjudul Representasi Politik, bahwa perkembangan representasi politik dapat diamati sejauh mana keberadaan Negara dalam pelaksanaan demokrasinya yang sangat dipengaruhi oleh perubahan fenomena politik. Viera dan Runciman mengatakan bahwa semua negara modern saat ini merupakan negara perwakilan. Representasi yang secara sederhana diartikan “menghadirkan yang tidak ada atau yang tidak hadir” berubah untuk memahami praktik politik demokrasi (Nuri Suseno, 2013:16).
Pada awalnya, menurut Hanna Pitkin representasi sepanjang sejarah tidak ada hubungan dengan demokrasi, ahkan tidak identik dengan demokrasi itu sendiri. Demokrasi dipandang sebagai pemerintahan rakyat sedangkan representasi adalah menghadirkan yang tidak hadir. Tentunya ini sangat berlawanan.Demikian pula yang dikatakan Benard Manin dalam The Principles of Representative Government (1997), pemerintahan perwakilan tidak sama dengan demokrasi (Nuri Suseno, 2013:26).
Menurut perspektif Manin dalam melihat state dan civil sebagai representasi politik dari perspektif demokrasi, lembaga yang dipandang sentral didalam pemerintahan perwakilan adalah “election” atau pemilihan dengan distinction.Sehingga dari election lahirlah wakil-wakil politik. Menurut Hanna Pitkin, dikatakan layak seseorang wakil dalam perspektif demokrasi adalah (1) authorization (otorisasi), (2) substantive acting for (tindakan mewakili dalam artian sesungguhnya), dan (3) accountability (pertanggungjawaban atau penanggunggugatan). Dari sini, paradigma yang semula menentang antara represtasi dengan demokrasi berbeda dapat menemukan benang merahnya (Nuri Suseno, 2013:30-31).
Repsentasi politik dari perspektif demokrasi cenderung dinamis, sebagaimana yang diungkap oleh Laura Montanaro. Montanaro melihat representasi politik dari intuisi normative demokrasi, bahwa representasi tidak harus dari election (representasi electoral) tetapi adanya self appointed representation yang berasal dari individu, kelompok masyarakat non pemerintahan (lokal, nasional, atau global). Demokrasi yang inklusif memungkinkan representasi politik yang tereklsusikan untuk hadir dan terwakili diarena pengambilan keputusan.
Keberhasilan penerapan politik identitas dalam hajatan politik sebelumnya termasuk dalam Pilpres 2019 telah menjadi raw model bagi beberapa daerah untuk menggunakan politik identitas sebagai pondasi utama bagi setiap kontestan untuk memenangkan pertarungan politik formal dan informal. Partai-partai sudah tidak lagi menjadi representasi dan wadah maupun alat untuk poses konsolidasi, dan komunikasi. Mendominasinya politik identitas dalam ruang publik yang sehari-hari sekarang terjadi dengan gelombang yang begitu besar di media sosial b ukan hal yang patut dirayakan, karena sepertinya media sosial juga turut andil terjadinya segresi sosial secara horizontal yang makin melebar.
Praktek demokrasi di Indonesia sepertinya telah beralih menjadi perlombaan yang tak mengenal kawan maupun lawan, semuanya dijalankan secara oligarchic democracy yang sangat akrab dengan politisasi bertendensi SARA dan memecah belah.Sentimen terhadap etnis minoritas yang terjadi hingga kini bisa jadi merupakan rekayasa sosial yang dikonsepsikan oleh kelompok tertentu untuk menarik simpati masyarakat
Bahaya dari politik identitas yang berlebihan adalah bisa berujungnya pada fasisme, bahkan lebih buruk lagi yaitu separatisme dan masyarakat yang sudah terasimilasi berdasarkan identitas tertentu, dapat dengan mudah dimobilisasi oleh kelompok yang ingin mencapai agenda politiknya. Politik identitas yang dijalankan oleh kelompok tertentu, berupaya memunculkan negara yang mono- identitas. Masyarakat Indonesia seakan dibuat hilang ingatan akan sejarah keragaman yang dimilikinya.
Secara singkat, politik identitas tak bisa dilawan dengan politik identitas “yang lebih lunak”. Ia harus dilawan dengan politik yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Hal lain yang juga perlu disikapi adalah jangan agama dibawa-bawa pada ranah politik. Agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral, baik dalam ranah individu maupun sosial, karena ajaran agama menekankan keimanan, ritual peribadatan, dan moralitas, Sedangkan politik menekankan aturan main dalam perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara, karena apabila agama digunakan sebagai sentimen pimodial dan etnisitas demi kepentingan politik, maka yang terjadi adalah politisasi agama yang berpotensi terjadinya kekerasan komunal secara horizontal, dan akibatnya spirit demokrasi yang sudah diperjuangkan dengan susah payah oleh kekuatan rakyat pada tahun 1998 akan sia-sia. Dilain pihak peran para pemimpin agama baik dari agama islam, protestan, katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu secara serempak bahu membahu harus mengarahkan umatnya untuk tidak terjebak dalam politisasi agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu demi memenuhi syahwat politik kekuasaannya.
Politik identitas : Penyakit demokrasi global
Dalam buku berjudul “The Good, the Bad, and the Ugly of Identity Politics” yang diterbitkan Princeton University, Amerika Serikat mencontohkan penggunaan politik identitas antara lain di Kanada, Israel dan Amerika Serikat. Dikutip dalam buku tersebut, in Canada, decided in 1990 to exempt a group from a long-standing rule governing their uniforms. Sikhs were exempted from wearing the wide-brimmed hat that is otherwise a required part of the Mounties’ official uniform. This exemption, while not in itself earthshaking, had far-ranging implications for the accommodation of diverse group identities by public authorities in Canada. The accommodation of the Sikhs in Canada met with six years of protest and was appealed to the Canadian Supreme Court, which refused to hear the challenge, leaving intact the exemption based on identity group membership (Di Kanada, pada tahun 1990 diputuskan Sikh dibebaskan dari mengenakan topi bertepi lebar yang dinyatakan merupakan bagian dari seragam resmi Mounties. Pengecualian ini, walaupun tidak dengan sendirinya merupakan gempa bumi, memiliki implikasi yang luas untuk akomodasi beragam identitas kelompok oleh otoritas publik di Kanada. Akomodasi orang-orang Sikh di Kanada bertemu dengan enam tahun protes dan diajukan banding ke Mahkamah Agung Kanada, yang menolak untuk mendengar tantangan itu, meninggalkan pembebasan yang tetap berdasarkan keanggotaan kelompok identitas).
Sementara, in Israel, also in 1990, a group of conservative and orthodox Jewish women petitioned the High Court of Justice to be given the same rights as Jewish men to pray in public. A year earlier, these women had peacefully marched to the Western Wall in Jerusalem, holding a Torah, determined to pray there without male approval. They were attacked by a group of mainstream orthodox Jews who were defending their religious prohibition of women from praying as orthodox men do in public.10 Ten years later, in 2000, the court recognized the women’s right to pray at the Wall without abuse by other worshippers. The court also held that the fact that their prayer offends other Orthodox Jews must not annul their ability to exercise their equal rights in public. In response to this ruling, the Israeli Knesset (the unicameral parliament of Israel) introduced a bill that would impose a penalty on any woman who violates traditional Orthodoxy by praying at the Wall (Di Israel, pada tahun 1990, sekelompok wanita Yahudi konservatif dan Ortodoks mengajukan petisi kepada Pengadilan Tinggi untuk diberi hak yang sama dengan pria Yahudi untuk berdoa di depan umum. Setahun sebelumnya, para wanita ini secara damai berbaris ke Tembok Barat di Yerusalem, memegang Torah, bertekad untuk berdoa di sana tanpa persetujuan pria. Mereka diserang oleh sekelompok orang Yahudi Ortodoks, kelompok arus utama yang membela larangan agama mereka terhadap wanita untuk berdoa seperti yang dilakukan pria ortodoks di depan umum. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2000, pengadilan mengakui hak wanita untuk berdoa di tembok tanpa disalahgunakan oleh yang lain. Pengadilan juga berpendapat bahwa fakta bahwa doa mereka menyinggung orang Yahudi Ortodoks lainnya tidak boleh membatalkan kemampuan mereka untuk menggunakan hak yang sama di depan umum. Menanggapi putusan ini, Knesset Israel (Parlemen Unikameral Israel) memperkenalkan undang-undang yang akan menjatuhkan hukuman pada wanita yang melanggar Ortodoksi tradisional dengan berdoa di tembok).
Sedangkan, in the United States in 1990, James Dale, an assistant scoutmaster of New Jersey Troop 73, received a letter revoking his membership in the Boy Scouts of America. Dale rose up through the ranks from cub to eagle scout to assistant scoutmaster. When executives in the Boy Scouts learned from a newspaper article that Dale was copresident of the Lesbian/Gay Alliance at Rutgers University, they revoked his membership. Dale brought suit against the Scouts on grounds of discrimination. The New Jersey Supreme Court ruled in Dale’s favor on the basis of the state’s antidiscrimination law (di Amerika Serikat pada tahun 1990, James Dale, Asisten Kepala Regu Kependudukan dari New Jersey Pasukan 73, menerima surat mencabut keanggotaannya di Kepramukaan Amerika Serikat. Dale naik melalui jajaran dari Cub ke Elang Scout ke Asisten Scoutmaster. Ketika eksekutif di Kepramukaan Amerikat Serikat mengetahui dari artikel surat kabar bahwa Dale adalah kepresiden Aliansi Lesbian/Gay di Universitas Rutgers, mereka mencabut keanggotaannya. Dale mengajukan gugatan terhadap Keprammukaan Amerika Serikat dengan alasan diskriminasi, kemudian Mahkamah Agung New Jersey memutuskan mendukung Dale atas dasar undang-undang anti-diskriminasi negara).
Mengancam Pilkada 2020
Politik identitas akan berlanjut pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, bahkan trennya menguat. Bagaimana pun juga, realitas politik yang terjadi di pesta demokrasi 2019 menjadi etalase eksploitasi politik identitas. Polarisasi berbasis irasionalitas politik identitas yang diterjemahkan dalam bentuk kampanye jahat, berita bohong (hoax), fitnah, dan politisasi SARA bakal menguat dalam Pilkada 2020 apalagi ditambah fakta yang taken for granted bahwa data terakhir menunjukkan ada 132 juta pengguna Facebook di Indonesia (nomor 4 terbesar di dunia), 50 juta orang pengguna twitter, dan 45 juta orang pengguna Instagram. Media sosial ternyata jadi pisau bermata dua. Media sosial bisa menjadi medium luar biasa berkembangnya kampanye jahat, hoax, fitnah, politisasi SARA dan politik identitas lainnya.
Akibat polarisasi di 2019, simbol-simbol politik di Indonesia menyadari bahwa politik identitas itu menjadi instrumen yang sangat ampuh dan murah untuk memobilisasi massa dan suara. Sebenarnya politik identitas hanya berlaku pada masyarakat dengan tingkat religius yang tinggi. Kemudian tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat ekonomi yang tidak begitu mapan.
Di beberapa hajat politik, baik Pilpres maupun Pilkada, masyarakat kerap jadi korban, ketika termakan narasi negatif. Cara ini merusak sistem demokrasi di Indonesia yang mengedepankan aspek keadilan berpendapat, termasuk memilih pemimpin berdasar keyakinan, visi-misi, program, kualitas, serta rekam jejak. Terlepas berasal dari suku atau agama apa pun itu.
Sebagai bangsa yang semakin cerdas berdemokrasi, sudah saatnya mengesampingkan hal-hal yang bersifat mendiskriminasi satu sama lain. Tujuan pemilu, idealnya memilih pemimpin yang amanah, jujur, dan bisa mensejahterakan rakyat. Masing-masing individu harus bisa mengutamakan sikap toleransi antarsesama umat manusia agar perpecahan bisa dihindari.
Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini untuk meminimalisir politik identitas dalam Pilkada 2020 dapat dilakukan dengan langkah bersama untuk mencegah politik SARA dan politik identitas di Pilkada 2020. Pertama, partai politik perlu mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas di Pilkada sehingga pertarungan di Pilkada tidak diwarnai oleh kampanye berbau SARA, tetapi pertarungan program-program membangun daerah. Kedua, menciptakan masyarakat yang melek digital. Karenanya pendidikan bagi warga untuk menjadi pengguna digital yang bijaksana mesti menjadi agenda prioritas berkesinambungan dan juga terkonsolidasi antar semua pemangku kepentingan terkait pemilu, meliputi KPU, Bawaslu, Kominfo, Kemdiknas, Kemdikti, Kempora, KPPPA, Kemendagri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia.