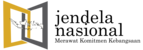Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — D*LIGHT Institute dan Yayasan LENO, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di House Of D*LIGHT Mandala Tomang Jakarta, pada Sabtu (5/10).
Diskusi itu menghadirkan Dr. Bennie E. Matindas, budayawan, penulis buku best seller “Negara Sebenarnya”, Direktur ISKA Center Ferlan Pangalia, S.H.,M.H. sebagai pembanding, dan moderator Emmanuel Yosafat Tular, S.IP, M.Si. Acara ini berlangsung selama sekitar 3 jam, dihadiri 30-an peserta dari berbagai kalangan termasuk anak muda.
Dengan tema “Mengurai Kebuntuan R-KUHP” Pucuk Gunung Es Kekusutan Fundamental Sistem Hukum Indonesia, Dr. Bennie E. Matindas sebagai pembicara tunggal memaparkan amatan dan refleksi atas apa yang diamatinya bertahun-tahun sebagai orang yang sering dimintai tulisan konseptual oleh pelbagai kalangan kelompok.
Menurut Bennie, apa yang disebut carry over atau pe-er (pekerjaan rumah) legislator baru itu sesungguhnya tidak ada harapan. Hopeless.
“Jangan kata tambah satu tahun lagi, saya pikir itu tak akan beres tuntas,” tegas Bennie penulis buku “Negara Sebenarnya” yang pernah akan masuk Rekor MURI sebagai buku teks referensi paling tebal (yang bukan kumpulan tulisan) di Indonesia melalui siaran pers di Jakarta, Senin (7/10).
Mengapa pernyataan pesimis dikemukakan Bennie? Bennie menjawab tegas, karena “kebuntuan ini sesungguhnya sudah terjadi di dasar, bukan di hal teknis hukum pidana itu sendiri”!
Bennie menyinggung justru pasal-pasal yang sudah puluhan tahun, bahkan sudah enam Presiden, dengan biaya sekitar 1 trilyun untuk dikirim ke luar negeri untuk studi banding. Puluhan profesor, bukan anggota DPR yang biasa melancong. Ingat pernah ada dua profesor berantem di TV, karena ketersinggungan soal ironis ini. “Sudah kelihatan, profesor-profesor pun sudah ada yang mati, tapi tugas ini jauh dari selesai,” lanjut Bennie.
Menurutnya, persoalan lebih mendasar adalah tentang “mengapa tidak pernah bisa mereka mencapai rumusan yang bisa diterima oleh sekedar akal sehat apalagi keadilan”.
Mengapa itu sulit dicapai sebuah rumusan. Bennie melanjutkan dengan menganalisis pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, sewaktu demo-demo mahasiswa yang marak saat rancangan ini berusaha diundangkan di akhir masa legislator periode 2014 – 2019 ini (30 September 2019). Menteri mengatakan bahwa hendak membuat koreksi total pasal-pasal yang berpotensi kriminal seperti tentang zinah. Dikhawatirkan ada kriminalisasi.
Menurut Bennie, pernyataan ini sebenarnya mengungkapkan bahwa pemerintah tampak sudah keasyikan dengan kata-kata seperti ini, tapi masyarakat termasuk para politisi tak bisa lagi melihat masalah di balik kata-kata itu.
Ini menyangkut hukum pidana dan itu menyangkut kehidupan kita semua warga sehari-hari. Apa bagaimana implementasi dan implikasinya?
Para ahli hukum sedunia masih memperdebatkan tentang apa yang disebut menghukum tingkah laku manusia. Mungkinkah, haruskah, bolehkah, dan atas dasar apa itu diberlakukan.
“Pernyataan Laoly bahwa beberapa pasal itu kemungkinan berpotensi menjadi kriminalisasi, itu memang kedengaran indah. Padahal memang demikian adanya bahwa masuk di pidana ya jelas kriminal,” ujarnya.
Persoalannya adalah benarkah bila pasal-pasal itu dimasukkan?
Bennie mulai menjawab lanjut secara agak filosofis dan historis. Pada akhir abad ke-18, para pemikir mulai memikirkan apa yang terjadi dengan filsafat yang selama itu dipersepsikan sebagai induk dari ilmu pengetahuan justru kalah jauh dari anaknya sendiri itu.
Apalagi memasuki abad ke-20 dengan tokoh Einstein yang membawa lompatan baru dalam dunia iptek, filsafat nampak ketinggalan di tempat malah meredup pengaruhnya.
Fenomena tertinggalnya filsafat ini melahirkan sekelompok filsuf yang menamakan diri Lingkaran Wina yang mengkritisi pencapaian segala ilmu-ilmu turunan tersebut. Mereka bahkan mengatakan ilmu hukum bukan pengetahuan, karena dia hanya aturan normatif belaka.
Tentu butuh penjelasan yang panjang terkait kritik dan perlawanan baru dari kalangan filsuf mashab kritis Wina ini. Tapi benar bahwa ini cukup untuk menggambarkan mengenai adanya kebingungan yang sifatnya fundamental. Padahal urusan permukaan kehidupan individu dan publik harus terus berjalan.
Yang sesungguhnya terjadi sekali lagi adalah di dasar rancangan undang-undang itu sudah terjadi gugatan.
Tentang kekhawatiran adanya potensi kriminalisasi, katanya, sebenarnya hanya soal bagaimana itu dirumuskan. Dan alasan di balik pernyataan kriminalisasi itu memang rasional dan etikal di dalam masyarakat sosial, akan tetapi masalahnya memang rentan dijadikan alat kesewenangan oleh pemerintah dan masyarakat.
Nah, ini menjadi makin runyam saat unsur agama masuk.
Menarik diperhatikan bahwa seolah terjadi polarisasi antar kubu, hanya karena yang satu memulai dan yang lain menolak, misalnya dalam rancangan UU Pornografi, tentang zinah.
Kalau dari kalangan Islam yang pro, maka yang non muslim langsung diposisikan sebagai atau mengambil sikap kontra. Misalnya dinyatakan bahwa seolah orang Minahasa, Bali, Mentawai itu contohnya gampang mentolelir saja soal kumpul kebo atau baku para itu, walau sesungguhnya melarang.
Juga dalam soal UU Sisdiknas, di kalangan muslim seolah sampai berkesimpulan bahwa orang kristen tak setuju dengan klausul anak didik mendapat pendidikan iman sesuai agamanya.
“Kebuntuan Abadi” RKUHP
Mengutip filsuf teolog skolastik Thomas Aquinas, Bennie menyebutkan bahwa optimisme dasariah untuk sebuah tatanan hukum yaitu bahwa manusia diformat oleh Pencipta untuk menerima kebenaran. Siapapun manusia itu dengan latar kepercayaan dan agama, bahkan sekular dan ateis sekalipun, tak luput dari hukum kodrat yang dalam filsafat Aquinas tidak mungkin bertentangan dengan hukum Ilahi.
Dalam kasus rancangan undang-undang pidana yang problematik karena secara fundamental sudah rusak dirusak itu, Bennie berani memperlihatkan apa dan mengapa sebuah dasar universal itu kehilangan isi inti dan energi dasarnya.
“Nullum delictum di pasal pertama adalah prinsip dasar sebuah kitab undang-undang hukum pidana yang umum berlaku di dunia: siapapun yang jahat akan dihukum! Tapi pasal ini disalib di tikungan oleh unsur agama,” ujarnya.
Tapi asas legalitas itu sekarang dimasuki oleh hukum tak tertulis termasuk hukum agama. Seolah agama bisa memaksakan atau menganulir sebuah hukuman?!
Memang fakta dan upaya ini sebenarnya wajar saja terjadi dan bahwa akan ada yang merasakan adanya ketidakadilan.
Karena itu, misalnya, sampai hari ini kelompok fundamentalis agama di Amerika, yang menjadi kampiun demokrasi dan hukum sekular, toh tetap berjuang memasukkan unsur agama Kristen sebagai mayoritas dalam undang-undang negara, walau hampir seluruh negara bagian sudah menolaknya.
Padahal dalam hukum internasional, agama tidak termasuk sebagai unsur yang bisa membatalkan penegakan hukum terkait HAM misalnya.
Karena persoalannya, kalau unsur agama dimasukkan, pertanyaan kritisnya agama apa, bahkan aliran apa, dan tafsir yang mana? Demikian plural dan perspektif terkait agama ini saja.
Contoh, denominasi gereja Protestantisme saja, sejak dipicu oleh Marthin Luther di Jerman pd abad ke-16 terhadap gereja Katolik Roma yang begitu berkuasa waktu itu — hampir 3 juta kelompok aliran (banyak yang sudah menghilang atau bereformasi menjadi lain, entah karena kekurangan duit atau masalah kepemimpinan, dll.) dengan ajaran dan tafsirnya masing-masing yang tidak sejalan.
Mereka bahkan saling menentang, bahkan saling mengkafirkan dengan segala implikasinya, termasuk sampai jatuh korban konflik berdarah-darah! Amerika Serikat itu adalah negara yang berdiri karena salah satunya oleh para pendatang yang tercabik-cabik dalam konflik teologi membabi buta di tanah biru Eropa jaya wijaya. Antara Katolikisme dan Protestantisme, dan antar denominasi gereja-gereja serta mashab teologi yang sangat beragam itu.
Sudah sejak jaman sebelum Masehi pun, di Romawi, filsuf Cicero sudah meniadakan agama dan segala unsur subyektif sistem keyakinan dari hukum negara.
Dan sejarah mencatat Kekaisaran Romawi kemudian menjadi negara yang kuat menguasai dunia peradaban yang sangat luas, dan kemudian menjadi rujukan segala hukum yang mempengaruhi dunia peradaban Barat bahkan mondial melalui kolonialisme dan kristianisme khususnya.
Kata Bennie, kalau sekarang di Indonesia, agama dimunculkan lagi, kiranya menjadi tanda bahwa sistem etika dan filsafat yang bersifat universal itu telah gagal.
Setiap hukum itu punya asas, norma, kaidah yakni dasar filosofis.
Adalah wajar kalau setiap ideologi (sebagai sistem filsafat) selalu akan masuk, misalnya pada jaman Nasakom Orde Lama, sewaktu PKI ada dalam lingkaran kekuasaan, ada banyak pengaruh unsur ideologi komunisme, selain unsur nasionalis dan agama, yang mewarnai undang-undang jaman itu. Dan pada saat Orde Baru berkuasa, semua anasir idiologi itu dibasmi sampai ke akar-akarnya. Penerapannya begitu ketat sampai-sampai ke segala sudut terkecil peraturan dan penerapan ya.
“Maka, belajar dari sejarah dan filsafat dunia, solusi atas ‘kebuntuan abadi’ rancangan KUHP ini sesungguhnya sederhana saja, yakni jalankan saja hukum itu tanpa tambahan dan intervensi lain-lain yang sifatnya parsial,” ujarnya.
Dengan itu kehidupan publik masyarakat serta perkembangannya bisa terus berjalan, bila hukum murni dijadikan patokan dan arah. Life must go on, apapun tuntutan identitas sosial dan problematiknya, yang sulit untuk diadopsi tanpa menyulitkan sistimatisasi sebuah hukum yang berlaku untuk semua, tanpa terkecuali.

Hanya Nilai dan Norma Rasional dan Universal
Bennie membuat kesimpulan ringkas untuk memudahkan para peserta dan memahami masalah untuk sebuah strategi bersikap dan bertindak dalam bingkai falsafah dasar Pancasila dan Konstitusi.
Upaya para politisi untuk memasukkan nilai serta norma agama ke dalam hukum nasional harus bisa dimaklumi, walau usaha mereka itu tidak sepenuhnya tepat, harus disempurnakan dulu.
“Memasukkan hukum agama ke dalam negara yang masyarakatnya plural haruslah hanya nilai dan norma-norma yang rasional universal. Norma yang hanya bernilai komunal, sektarian, parokial, terlebih yang irasional subyektif, pasti menjadi ketidakadilan atas kelompok warga lainnya, dan nilai tak adil tentu bertentangan dengan fitrah hukum,” ujarnya.
Bennie mengatakan, kita perlu memaklumi upaya kelompok politik keagamaan untuk memperjuangkan agamanya menjadi falsafah dasar hukum itu, walau sudah dalam era modern sekarang.
Karena justru modernitas itulah yang menyajikan pengalaman betapa semua ideologi dan filsafat sekuler itu terbukti bukan saja gagal mencapai janji-janji kemakmuran melainkan pula memurukkan umat manusia dalam dekadensi moral yang parah, kegersangan batin, (kata Ivan Illich:) reifikasi yang subhumanisasi, manusia merosot ke bawah standard homo sapiens.
Sementara janji kemakmuran hanya menghasilkan ketimpangan yang lebar dan pasti menyuburkan ketidakadilan.
Para ahli hukum sekuler sudah mengusahakan pelbagai solusi, seperti John Austin, Hans Kelsen, dan memuncak pada Herbert Hart, dengan Positivisme Hukum-nya, juga ada Hugo Krabbe, Duguit, Geny, yang memuncak pada Roscoe Pound, dengan falsafah hukum sosiologikalnya (yang mengandalkan teori epistemologi Rousseau, Kant, Hegel dsb).
Tapi masing-masing mereka memiliki kelemahan mendasar. Begitu juga pelbagai ideologi nasional yang mencoba menggabungkan unsur filsafat sekuler dan agama, belum mencapai hasil memadai bahkan di tataran teoretis.
Di Indonesia, ideologi Pancasila, kata Bennie, sebagaimana kritik yang sangat terkenal dari St. Takdir Alisjahbana, belum memenuhi syarat sebagai filsafat, karena belum koherens.
Para ahli dan para pemimpin bangsa ini mengakui kebenaran kritik tersebut lantas mengusahakan sistematikanya yang koheren. Beberapa mencapai hasil yang signifikan, seperti yang diajukan Bung Hatta pada 1956, Prof. Drijarkara pada 1958, dan Prof Mukti Ali pada 1977.
Sedang lainnya melantur lucu, seperti yang diajukan Prof Notonagoro dari UGM, tapi dialah malah yang paling sering dirujuk sampai sekarang. Gara-gara soal kebenaran filosofis Pancasila selalu hanya dijadikan soal politik, bukannya epistemologis.
Rumusan Bung Hatta tak diterima karena Desember tahun 1956 itu juga ia meletakkan jabatan Wapres dan kemudian dicap pro-PRRI/Permesta. Begitu pula Mukti Ali thn 1977, tapi Maret 1978 penguasa Orde Baru sudah mengkonstitusikan dogmatisasi Pancasila versi P4.
Karena itu, Bennie mengajak para peserta untuk belajar dari sejarah bangsa sendiri yang tak lepas dari pemikiran dan pengaruh filsafat dunia, yang selalu mencintai dan karenanya mencari kebenaran itu, dengan iman tulus murni dan rasio kritis jernih. Historia magistra vitae est, sejarah adalah guru kehidupan.
“Pahami dan syukuri apa yang ada, termasuk hal keberbedaan dan perbedaan sebagai yang dikehendaki Allah sendiri, walau fakta terberi telah pernah menjatuhkan fitrah manusia luhur suci ciptaan itu karena tidak bijak, tidak memakai segala daya mental dan kodrat spiritualya sendiri yang berorientasi kehidupan final dan ultim, yang antisipasinya diusahakan di dunia fana ini menjadi perjuangan menjadi manusia yang sebaik-baiknya adalah berguna bagi kehidupan, bukan lawan kehidupan secara pribadi individual, komunal kelompok, dan publik warga Indonesia bahkan Masyarakat global,” pungkasnya. (Ryman)