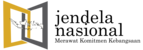Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutan NO.REG.PERK:PDM-0490/Denpa/KTB/07/2020 dalam perkara nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps menuntut penjara tiga tahun dan denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan atas kasus yang menimpa I Gede Ary Astina alias Jerinx, dalam sidang pada Selasa (3/11).
Jerinx diduga melakukan ujaran yang berisi penghasutan untuk melakukan suatu tindakan kebencian/kekerasan/diskriminasi berdasarkan SARA atau pencemaran nama baik.
Jerinx, pemilik akun Instagram @jrxsid sebelumnya didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 UU ITE Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai ujaran kebencian ATAU pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik.
Jerinx dilaporkan oleh IDI wilayah Bali atas postingannya yang menyebut IDI sebagai “kacung WHO” karena mewajibkan dilakukannya rapid test.
“ICJR berpendapat, penggunaan pasal pidana UU ITE untuk menjerat Jerinx atas postingan yang dibuatnya ini tidaklah tepat. Penahanan sampai dengan tuntutan pidana penjara yang dikenakan terhadapnya pun tidaklah perlu untuk dilakukan dan cenderung dipaksakan. Adapun pernyataan Jerinx terhadap penanganan Covid-19 yang kontraproduktif perlu menjadi pemicu untuk menghadirkan diskursus publik yang lebih sehat, ketimbang menggunakan jalur kriminalisasi melalui instrumen UU ITE,” ujar Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus A.T. Napitupulu melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (5/11).
ICJR juga menemukan permasalahan dalam tuntutan tersebut.
Pertama, Penuntut Umum (PU) melakukan kesalahan dalam membuktikan unsur kesengajaan.
Dalam tuntutan, membuktikan dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU ITE Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur salah satunya unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”.
JPU menguraikan panjang lebar tentang unsur ini dengan menyimpulkan “Bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini, adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya dan terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu”. Namun pada uraian selanjutnya JPU justru mengaitkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak tersebut dengan Pasal 27 ayat (3) UU UU ITE dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, bukan dengan pasal yang sudah dipilih oleh JPU yaitu Pasal 28 ayat (2) jo.
Pasal 45A ayat (2) tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat.
“Ini adalah kesalahan mendasar dalam suatu tuntutan, karena unsur kesengajaan justru tidak dikaitkan dengan perbuatan yang dituntut. Catatan penting, unsur kesengajaan adalah unsur yang krusial dalam pembuktian kasus ujaran kebencian,” ujarnya.
Kedua, JPU tidak mampu sepenuhnya membedakan antara penghinaan/pencemaran nama baik dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat atau ujaran kebencian.
Sedari awal dakwaan bahkan sampai dengan tuntutan, JPU sama sekali tidak menjelaskan apa unsur yang saling mengecualikan antara Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sedangkan kedua ini jelas memiliki tujuan pengaturan dan rumusan yang berbeda, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan untuk perbuatan melakukan penghinaan secara Individu melalui tuduhan untuk diketahui umum sebagaimana harus merujuk pasal 310/311 KUHP, merupakan delik aduan absolut sehingga korban harus disebutkan namanya secara tegas dan jelas untuk memastikan adanya kesengajaan dengan tujuan merendahkan martabat orang.
Sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak harus bersifat “tuduhan” melainkan informasi yang merupakan penghasutan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, dengan berdasarkan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), bukan Individu. Sedangkan uraian yang dibuat oleh JPU dalam tuntutan tidak sama sekali jelas menguraikan perbedaan ini, malah fakta persidangan dicampuradukan.
Ketiga, JPU melakukan kesalahan, seolah IDI adalah pihak yang dilindungi oleh pasal ujaran kebencian.
Ujaran kebencian dikriminalisasi dengan tujuan yang baik, yaitu melindungi kelompok-kelompok dari praktik diskriminasi. Pasal ini ditujukan untuk melindungi orang-orang, kelompok orang atau komunitas dari tindakan diskriminatif.
Yang dikriminalisasi adalah perbuatan mengutarakan kebencian tentang kebangsaan, rasial atau kelompok agama yang membuat risiko diskriminasi yang akan segera terjadi, permusuhan atau kekerasan terhadap orang termasuk dalam kelompok tersebut akan terjadi.
Hal ini berbeda dengan kritik terhadap suatu institusi. Dalam kaitannya dengan tokoh publik ataupun organ publik adalah subjek dari kritik dan oposisi. Dalam kacamata negara demokratis, negara tidak seharusnya melarang kritik pada institusi.
“IDI bukan kelompok yang tidak bisa dikritik. Pernyataan Jerinx harus dipisahkan dengan narasi ‘kehormatan dokter’ ‘ketersinggungan dokter’ karena pernyataan Jerinx berkaitan dengan kebijakan, yang mengandung aspek kepentingan umum, hal tersebut tidak berkaitan dengan perasaan dokter secara individual,” ujar Erasmus.
Keempat, JPU dalam tuntutan tidak menguraikan secara komprehensif bahwa apakah yang diutarakan jerinx benar ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, dengan berdasarkan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Secara internasional, titik ujaran kebencian harus melalui enam bagian (six part incitement test) untuk dapat mengetahui apakah sebuah ekspresi masuk kualifikasi sebagai penyebaran ujaran kebencian, terlebih dahulu harus dilihat: (1) Konteks di dalam ekspresi; (2) Posisi dan status individu yang menyampaikan ekspresi tersebut; (3) Niat dari penyampaian ekspresi untuk mengadvokasikan kebencian dan menghasut; (4) Kekuatan muatan dari ekspresi; (5) Jangkauan dan dampak dari ekspresi terhadap audiens; dan (6) Kemungkinan dan potensi bahaya yang mengancam atas disampaikan ekspresi.
Tuntutan dalam perkara nomor 828/Pid.Sus/2020/PN tidak sejalan dengan six part incitement test ini. Walaupun kekuatan muatan dari ekspresi yang disampaikan Jerinx bisa bersifat provokatif akan tetapi IDI merupakan kelompok profesi dan bukan kelompok sebagaimana dimaksud di dalam kelompok SARA, dan IDI bukan kelompok yang tidak dapat dikritik.
Erasmus mengatakan, posisi Jerinx sebagai musisi yang lantang berisi kritik terhadap pemerintah harus juga dipertimbangkan, catatan mendasar, ekspresi dalam debat publik dalam masyarakat demokratis yang ditujukan pada domain/ institusi publik batasannya sangat tinggi, artinya ekspresi ini sangat dilindungi.
Niat untuk “menghasut” tidak terpenuhi dari ekspresi yang disebut Jerinx. IDI bukan pihak yang harus dilindungi dengan pasal ujaran kebencian, IDI adalah institusi yang selalu bisa dikritik.
Karena itu, penahanan dan sekarang tuntutan penjara pada Jerinx adalah suatu kemunduran bagi negara demokratis. Pada perkembangannya pun apa yang dikritik oleh Jerinx dikoreksi dan diakui oleh pemerintah, yang kemudian direspon pada pengubahan kebijakan, maka pernyataan Jerinx tersebut adalah ekspresi sah yang bermuatan kepentingan publik.
“Jika Jerinx atas kritiknya bisa dipenjara, maka bukan hal yang tidak mungkin kritik-kritik lain yang merupakan ekspresi sah bisa dipidana,” pungkasnya. (Ryman)