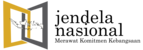Jakarta, JENDELANASIONAL.ID – Wacana Jokowi sebagai Cawapres 2024 yang muncul belakangan tidak berdiri sendiri. Hal tersebut senada dan beriringan dengan wacana yang lebih dulu dimunculkan yaitu terkait jabatan presiden tiga periode dan wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Jika ditanyakan isu-isu itu dari siapa, ada yang menduga dari kelompok loyalis Jokowi yang masih tergoda untuk melanggengkan kekuasaan.
Kemunculan isu terakhir Jokowi maju cawapres, boleh jadi dari sumber yang sama atau bisa pula bersumber dari kejumudan publik dalam melihat bursa capres-cawapres yang itu-itu saja dengan menapaki stagnasi elektabilitas.
Padahal, semestinya masih cukup waktu untuk menawarkan banyak tokoh terbaik bangsa sebagai figur capres atau cawapres alternatif untuk memeriahkan Pemilu 2024.
Hal itu mengemuka dalam diskusi PARA Syndicate dalam diskusi publik yang bertajuk “Jokowi Cawapres 2024 vs Capres-Cawapres Alternatif”, pada Rabu, 21 September 2022, di Jakarta.
Jika dirunut, bergulirnya wacana bahwa Presiden Jokowi akan diajukan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024, muncul setelah Juru Bicara Mahkamah Konstitusi mengungkapkan tafsirnya mengenai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7. Sang Jubir menyebutkan bahwa presiden, dalam hal ini Jokowi, yang sudah menjabat selama dua periode bisa dipilih sebagai wapres.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai bahwa wacana ini sejatinya mencerminkan adanya kondisi stagnasi dalam perpolitikan nasional.
Menurutnya, dalam menapaki jalan elektoral menuju Pilpres 2024, Indonesia saat ini sedang mengalami disorientasi politik dan disorientasi demokrasi.
“Ada tiga hal yang menyebabkan disorientasi politik saat ini, yaitu adanya sindrom Jokowi, sindrom survei, dan de-capresinasi partai politik,” ujar Ari.
Ia menjelaskan sindrom Jokowi merupakan kondisi kenyamanan bersama pemerintahan Jokowi sehingga mengharapkan Jokowi tetap langgeng.
Sementara itu, sindrom survei menunjukkan figur capres cawapres yang hanya itu-itu saja dengan elektabilitas jenuh di kisaran 30-an persen – yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Kondisi ini kemudian membuat beberapa partai politik ragu dan tak berani mengajukan figur-figur baru sebagai capres-cawapres alternatif. Kita mengalami de-capresinasi parpol.
Sementara itu, disorientasi demokrasi saat ini terjadi lantaran kekuatan oligarki yang mendominasi dalam membentuk preferensi politik yang mengarah ke figur yang itu-itu saja. Prinsip demokrasi itu membatasi dan mengontrol kekuasaan, dengan menerapkan pergantian dan regenerasi kekuasaan.
“Dalam politik juga berlaku bahwa nobody is indispensable (tidak ada yang tak tergantikan), dan saat ini kelihatannya ada sebagian kita yang merasa Jokowi seperti tidak tergantikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Ari mengatakan bahwa publik perlu memunculkan banyak figur lain untuk meramaikan bursa Pilpres 2024 agar dipertimbangkan menjadi capres-cawapres alternatif, baik dari unsur partai maupun nonpartai.
“Capres alternatif dari partai ada Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Sandiaga
Uno; dan dari nonpartai ada Andika Perkasa, Tito Karnavian, dan Rizal Ramli. Cawapres alternatif dari partai disebut Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno; dan dari nonpartai ada Erick Thohir, Sri Mulyani, Retno Marsudi, dan Budi Gunadi Sadikin,” kata Ari dalam paparannya.
Pemilu Substantif
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Aqidatul Izza Zain menyayangkan bahwa kandidasi capres-cawapres yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik memang cenderung tertutup. Prosesnya tidak melalui mekanisme terbuka.
“Ini tertutup dan biasanya didominasi oleh elit-elit partai politik itu sendiri. Jadi, elit partai yang akan menentukan capres-cawapres. Sering kali, kader partai politik kurang atau tak dilibatkan dalam proses kandidasi itu. Sehingga sulit untuk memunculkan nama baru atau capres-cawapres alternatif,” kata Izza.
Ia menilai, di satu sisi hal ini merupakan konsekuensi dari presidential treshold atau ambang batas pencalonan capres-cawapres yang mensyaratkan 20 persen kursi partai di DPR.
Karena itu, di sisi lain mestinya partai politik membuka opsi mekanisme kandidasi capres-cawapres secara terbuka di internal partai.
Izza mendorong partai untuk menerapkan mekanisme lain dalam proses kandidasi capres dan capawres. “Misalnya saja dengan mekanisme konvensi atau menggelar pemilu pendahuluan di internal partai politik atau gabungan partai politik itu sendiri,” imbuh Izza.
“Lalu perlu dipastikan capres-cawapres itu lahir dari proses demokrasi yang sah di internal partai, dengan begitu membuka ruang untuk berdemokrasi jadi lebih luas, dari anggota parpol bahkan hingga simpatisan. Dari mekanisme ini kemudian diharapkan dapat memunculkan capres-cawapres alternatif,” pungkas dia.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus menambahkan bahwa sekarang ini memang sebaiknya dimunculkan figur-figur baru. Figur baru ini punya peluang untuk diorbitkan, mengingat figur yang disorot papan atas survei saat ini atau punya elektabilitas tinggi belum menawarkan program sama sekali.
Selain itu, ia juga menilai bahwa publik sudah jenuh dengan figur yang itu-itu saja. Lucius prihatin bahwa kandidasi pilpres hanya berorientasi kursi kekuasaan, bukan demi membangun mimpi untuk Indonesia masa depan.
“Belum ada figur yang menawarkan program, mengungkapkan apa yang ingin mereka lakukan untuk membangun mimpi Indonesia, hingga visi-misinya ke publik jika mereka dipilih menjadi presiden dan wapres. Jadi, sekalian saja dimunculkan figur baru atau capres-cawapres alternatif. Apalagi publik tampaknya sudah jenuh dengan figur yang itu-itu saja,” tegas Lucius.
Lucius berpendapat bahwa ada banyak figur yang punya potensi, kapasitas, dan kualitas untuk menjadi capres-cawapres sesuai yang dibutuhkan Indonesia.
“Namun, karena kita tidak dekat dengan partai politik, maka mereka cenderung jauh dari radar,” ujarnya.
Lucius menambahkan bahwa kita semua perlu mendorong pemilu substantif, pemilu yang mengusung gagasan dan program.
Selain itu, Lucius menekankan pentingnya bagi publik untuk membaca kebutuhan sebelum memilih capres-cawapres alternatif. “Ini cukup mendesak mengingat pemilu akan digelar di 2024,” ujarnya.
Bahkan, katanya, seharusnya soal kebutuhan publik mestinya banyak dibicarakan dan jadi wacana. “Akan lebih mudah memastikan kebutuhannya dulu, baru kemudian dicocokkan dengan figur-figur yang ada. Bukan figurnya dulu, baru membahas pemenuhan kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat untuk membangun Indonesia dan mewujudkan visi-misi ke depan harusnya didahulukan,” tutupnya. ***