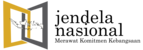Jakarta, JENDELANASIONAL.ID — Pemerintah menggunakan berbagai macam istilah dalam penangangan pandemi Virus Covid-19. Pada suatu waktu, pemerintah menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pada waktu lain menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dan PPKM Level 1-4.
Parahnya, penggunaan berbagai macam istilah tersebut tidak jelas dasar hukumnya. Buntutnya, hal itu membuat masyarakat menjadi bingung.
“Ini salah satu kegagalan komunikasi pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Karena menggunakan istilah yang membingungkan publik hanya karena pemerintah tidak mau menggunakan UU Karantina,” ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio di sela-sela acara vaksinasi di Kompleks Rumah Saya, Jalan Batu 1 No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (27/7).
Agus mengatakan, istilah PSBB maupun PPKM yang digunakan pemerintah tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Padahal dalam undang-undang disebutkan dengan jelas tentang adanya UU Karantina Wilayah.
“Karena itu, saya tidak tahu yang namanya PSBB dan PPKM itu dasar hukumnya apa. Jadi berat itu. Makanya sulit sekali mengatur masyarakat dan dunia usaha karena pemerintah mengambil jalan pintas yang kita tidak tahu alasannya apa,” ujarnya.
Selain itu, kata Agus, selain menggunakan istilah yang tidak jelas dasar hukumnya, pemerintah juga menggunakan peraturan pelaksanaan yaitu berupa Surat Edaran (SE) yang juga tidak ada dalam tata peraturan perundang-undangan.
Agus mengatakan UU Nomor 12 tahun 2011 atau kemudian yang diperbaharui dengan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki perundang-undagan. Berdasarkan hirarki peraturan tersebut, tidak ada nama Surat Edaran.
“Hirarki perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jadi tidak ada itu namanya Surat Edaran. Jadi Surat Edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Karena tidak berkekuatan hukum maka dia tidak bisa mengatur publik,” ujar Agus.
Surat Edaran, kata Agus, adalah surat internal terkait kebijakan dalam sebuah kementerian/lembaga dan tidak bisa mengatur masyarakat luar, termasuk pemberian sanksi kepada masyarakat. “Tapi saya tidak tahu mengapa hal itu dipakai,” kata Agus.
Terkait pemberian sanksi, menurut Agus, diatur di dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Nah dia mau nyantol di mana, saya juga tidak tahu. Itu yang menyebabkan para petugas di lapangan mengalami kesulitan dalam menjalankan peraturan tersebut. Misalnya polisi atau Satpol PP mereka menjadi bingung karena banyaknya SE (Surat Edaran) yang dikeluarkan oleh pemerintah,” kataya.
Hal itu juga, kata Agus, yang menyebabkan banyak kepala daerah akhirnya tidak menyalurkan APBD karena takut akan bermasalah di kemudian hari. Padahal pemda sudah membelanjakan barang untuk keperluan tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Namun, pemda tidak bisa menyalurkannya. Apalagi, SE tersebut tidak memiliki petunjuk tenis (juknis) yang jelas. Kemudian pemerintah daerah kembali menghadapi berbagai perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang juga berubah-ubah.
“Mereka (kepala daerah) tidak berani mengeluarkan duit karena takut nanti akan diperiksa oleh BPK, dan mereka bisa salah,” ujarnya.
Agus mengatakan, hal seperti ini bukannya tidak diketahui oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan dalam berbagai wawancara dirinya selalu ditanyai terkait hal tersebut. Dan dia juga sudah berulang kali menyampaikannya kepada pemerintah, seperti kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara.
“Saya sudah berulang kali ditanyai wartawan terkait hal ini. Saya juga sering menanyakan hal ini kepada para profesor hukum tata negara dan mereka juga merasa heran,” ujarnya.
Tidak Jelas yang Bertanggung Jawab
Terkait alasan pemerintah enggan menggunakan UU Karantina, alumnus Sekolah Menengah Atas Negeri III Teladan Jakarta itu mengatakan karena sedari awal pemerintah tidak mau mengeluarkan uang atau memberi makan rakyatnya.
“Nah waktu itu untuk menghindari kasi uang rakyat. Dan pemerintah takut jika lockdown itu maka ekonomi kita akan hancur. Tapi apa yang terjadi sekarang ini yaitu kebijakan di dua kaki itu (kesehatan dan ekonomi) malah ekonomi menjadi hancur dan pandemi berkepanjangan,” ujarnya.
Yang terjadi saat ini, katanya, yaitu tidak jelasnya pihak yang bertanggung jawab dalam menangani pandemi. Juga terkait komunikasi, katanya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab.
“Selain itu siapa yang paling bertanggung jawab, apakah Menteri Kesehatan, Gugus Tugas, Satgas atau Pak Luhut (Binsar Pandjaitan). Di daerah bilang ini tanggung jawabnya Ketua Penanggung Jawab Covid-19 Bapak Luhut. Tapi terus suratnya mana. Dan mereka jadi bingung. Itu yang membuat penanganan pandemi ini tidak bisa jalan,” ujarnya.
Masih ada satu dua kepala daerah yang memiliki terobosan inovatif dan kreatif dalam penanganan pendemi ini, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun, kata jebolan Engineering & Applied Science di the George Washington University Amerika Serikat itu pemerintah daerah membutuhkan dasar hukum dari semua kebijakannya tersebut.
Karena itu, mantan pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) itu pesimistis terhadap penyelesaian kasus pandemi Covid-19 di tanah air bisa berjalan cepat dan efektif. “Makanya ribet, siapa yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)