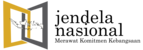Oleh : Yustinus Prastowo
Desember 1993, sebuah gambar muncul di halaman pertama media milik kelompok Hutu di Rwanda. Tertulis besar dan jelas di situ “What Weapon Can We Use to Defeat the Inyenzi (kecoa dalam bahasa Tutsi) Once and for All?” Beberapa bulan kemudian, genosida terjadi, meski ini bukan sebuah patahan kejadian tanpa konteks.
Sebagaimana dibabar Judi Rever dalam “In Praise of Blood”, fakta menunjukkan pemberontak Rwandan Patriotic Front (RPF) yang mayoritas Tutsi dan didukung Uganda dan Washington pun melakukan pembantaian yang tak kalah keji. Namun pesan penting dari sejarah kelam ini tetap layak dikenang: hati-hatilah dalam berkata-kata!
Terkesan sepele, menggunakan kata ‘kecoa’ namun dampaknya tak terduga: ratusan ribu nyawa melayang sia-sia. Lantas kenapa kita pun gemar bermain-main dengan ragam istilah hewani: cebong, kampret, kecoa, atau sapi? Apakah kita menyadari implikasi yang bisa sedemikian buruk? Memang Indonesia bukan Rwanda, tak perlu ada kekhawatiran tentang genosida. Namun poin pentingnya bukan itu.
Mengapa kita tak mulai mencegah untuk terlalu mudah mengobral kata-kata yang berpotensi membuat luka dan melanggengkan ketegangan, bahkan menciptakan permusuhan? Apakah perbedaan politik lantas absah menjadi pembenaran untuk menista dan menegasi eksistensi liyan?
Jelas, bangsa ini didirikan di atas imajinasi kolektif, yakni kesamaan nasib dan cita-cita. Perbedaan di antara para pendiri bangsa adalah fakta – baik suku, agama, ideologi – namun itu bukan halangan, justru menjadi modal kuat untuk bersatu dan bekerja sama. Lantas kini kita hendak mengoyaknya?
Berguru pada praktik relasi antarpendiri bangsa, kekaguman kita akan memuncak ketika kita tak sekalipun mendapati ketegangan dan perbedaan amat tajam mereka selesaikan dengan ungkapan ‘dungu’ atau ‘tolol’ misalnya.
Entah lantaran istilah itu belum dikenal kala itu, atau memang para pendiri Republik yang bijak bestari dan ugahari itu tak memiliki idiom itu. Ada adab dalam beda, dan persis itulah yang menghilang hari-hari ini.
Ucapan-ucapan hewani yang bernada merendahkan direproduksi, dugaan saya, selain untuk menutup pintu dialog juga untuk membuat garis batas ‘aku-kamu’ atau ‘kami-mereka’ secara jelas dan tegas.
Kita tak sadar implikasinya: mengabaikan eksistensi dan merendahkan martabat sesama. Lantas kita kehilangan ciri khas Indonesia: kekitaan. Sebuah kekayaan, yang oleh Fuad Hassan disebut khas Indonesia lantaran tak ada bangsa lain memilikinya.
Kita bukan tak sadar menciptakannya dan harus merawat dan menghidupinya. Ruang publik menciptakan ironi: perayaan kebebasan itu tak dibarengi sikap etis yang memadai. Bahkan kerap jemari ini bertindak melampaui kecepatan bernalar. Kita diam-diam memupuk perilaku pengecut: menyiram bara lalu mengelak dan bersembunyi dalam anonimitas.
Percakapan di media sosial semakin riuh dan gaduh. Banjir informasi yang sedemikian dahsyat tak menyisakan waktu dan jarak untuk bercermin dan merenung. Tak terasa kita pun semakin terkotak-kotak, berkumpul secara alamiah dengan teman yang punya ide, warna, dan pilihan sama. Algoritma menuntun kita semakin kerdil dan picik.
Group-group WhatsApp menjamur, namun semakin homogen dan dangkal. Dan sialnya, kita terpuaskan ketika melampiaskan kecemasan atau aspirasi di hadapan fora yang isinya seragam. Karena kita tak butuh diskusi, lawan debat, atau konfrontasi gagasan. Kita butuh ketenangan, afirmasi, dan dukungan.
Apapun, kita butuh jalan keluar. Jika cara terbaik merawat masa depan adalah dengan berguru dan memeluk masa lalu, maka belajar pada para guru bangsa seyogianya menjadi pilihan pertama. Kita pernah memiliki negarawan-negarawan paripurna dan sempurna.
Mereka dididik oleh budaya baca yang hebat dan ditempa oleh pergumulan fisik yang dahsyat. Tak perlu muluk-muluk bicara tentang mimpi Indonesia di masa depan, namun merenung apakah kita masih layak disebut satu bangsa, jika terus mengoyak diri dengan perendahan sesama anak bangsa.
Kenapa kita sulit menghargai prestasi dan pencapaian orang lain? Mengapa kita kerap terburu-buru ingin menghakimi, bukan diam dan tekun mendengar?
Boleh jadi kita kehabisan stok negarawan. Tapi media sosial justru memberi kesempatan bagi tiap orang menjadi pahlawan, terkenal, dan dinilai baik. Kita musti mengembalikan ‘yang sosial’ pada media sosial, supaya ketegangan itu sedikit melentur dan kekerasan hati melunak. Saya dan Anda barangkali bukan pengamat yang baik dan berpretensi paham apa yang terjadi.
Sebagai pelaku, tentu saja tiap kita tak akan luput dari irasionalitas dan emosi, menjadi bagian dari masalah. Barangkali kini saatnya kita memulai dari diri kita dengan berhemat kata-kata jika itu berpotensi menimbulkan luka.
Saatnya kita merawat taman keragaman yang diwariskan pada kita, dengan kesediaan menenggang dan menerima liyan, apa adanya – tentu saja dalam bingkai nilai dan visi kebangsaan yang disepakati. Ruang-ruang perjumpaan ragawi yang dipenuhi ekspresi alami perlu diperbanyak, sebagai alternatif media sosial. Kita musti yakin bisa dan ingin melakukannya.
Melampaui segala intrik, mari kembalikan politik dan ruang publik pada marwahnya, sebagai sarana meraih kebaikan bersama, bukan cuma segelintir orang atau kelompok tertentu, karena kitalah pemilik Indonesia.
Mari tunduk kepala sejenak dan memanjatkan doa dan harapan terbaik untuk bangsa kita tercinta, dengan kata-kata terindah yang muncul dari sanubari yang bening, menyapa, dan memeluk erat tiap kita, sebagai sahabat dan anak bangsa. Karena kita tidak lantas menjadi baik dan benar hanya karena menganggap ada orang lain yang keliru dan buruk.