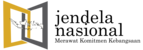Oleh: Dr. Hendro Setiawan
Orang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, membusungkan dada dan berkoar: “aku benci politik!”. Sungguh bodoh dia, yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk: korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri.
Berthold Brecht, Penyair daan Dramawan Jerman
Dalam sistem demokrasi yang dianut mayoritas negara-negara di dunia saat ini, politik adalah sarana utama. Sarana untuk menjadikan kehendak rakyat sebagai tujuan. Sarana untuk mewujudkan: “dari rakyat, demi dan untuk rakyat”. Sarana untuk membawa tatanan masyarakat menuju kebaikan tertinggi. Perkembangan suatu negara sangat ditentukan oleh perpolitikan di negara tersebut. Politik yang baik membawa negara pada kebaikan, dan sebaliknya politik yang buruk pada kehancuran.
Dengan dasar kekuasaan tertinggi pada rakyat (warga negara), sistem demokrasi bergantung kuat pada tingkat kesadaran politik warga negaranya. Makin tinggi tingkat kesadaran politik warga negara, makin baik sistem demokrasi berfungsi dan makin baik pula kebaikan umum yang dihasilkan. Kesadaran politik dapat menjadi titik lemah sistem demokrasi, ketika mayoritas warga negara kurang memahaminya. Penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan elit, korupsi, kolusi, nepotisme, dan dampak negatif lainnya, dapat merajalela akibat kurangnya kesadaran politik warga negaranya. Berbagai permasalahan pada banyak negara yang berkembang telah membuktikan hal ini.
Di Indonesia, mayoritas partisipan politik justru masih berpendidikan rendah. Statistik menunjukkan bahwa hampir 50 % rakyat indonesia masih berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Indonesia juga negara yang “relatif” masih muda dalam berdemokrasi (dihitung sejak kemerdekaan, “baru” 73 th), apalagi jika dibandingkan dengan USA yang sudah 250 th. Dengan demikian mayoritas warga negara Indonesia yang berpengaruh menentukan arah politik dan perkembangan negara justru belum memiliki tingkat kesadaran politik yang memadai. Akibatnya dalam peristiwa pemilihan politik, banyak aktor/aktris justru dengan mudah mendapat suara. Visi, misi, kemampuan memimpin, dll, yang seharusnya menjadi kriteria utama, justru cenderung terabaikan. Padahal, pada mereka yang terpilih inilah masa depan bangsa ini digantungkan. Dengan demikian, apabila perkembangan negara ini masih belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan, siapa yang salah?
Lalu, bagaimana membangkitkan kesadaran politik mayoritas warga negara? Khususnya umat Katolik? Yang kebanyakan masih sederhana dalam pola pikir? Atau malah terjangkit “alergi politik”? Ditengah masih kuatnya kecenderungan “pastor sentris”, dimana pastor jelas bukan dikhususkan sebagai ahli politik? Ditengah kerumitan dunia politik yang membingungkan dan maraknya hoax-hoax politik? Darimana para umat Katolik mendapatkan landasan bagi keputusan politiknya? Siapa atau partai apa yang harus dipilih? Apa kriteria yang benar? Bagaimana pula partisipasi politik diluar masa pemilihan? Apalagi yang harus dilakukan, ditengah segala kerumitan hidup sehari-hari?
Iman Katolik, sejak awal menuntut partisipasi dalam karya Allah menciptakan dunia yang lebih baik. Ini sering ditegaskan dengan istilah “perutusan”. Setiap Ekaristi selalu ditutup dengan pernyataan perutusan (“…. marilah pergi, kita diutus….”). Injil Matius menutup seluruh kisah tentang Yesus dengan tema: perintah untuk memberitakan Injil (Mat 28: 16-20). Hal yang senada juga pada akhir Injil Markus. Injil Yohanes pada bab terakhir mengangkat tema perintah Yesus pada Petrus: Gembalakanlah domba-dombaKu (Yoh 21: 15-17). Inkarnasi Yesus adalah manifestasi kesediaan Sang Putra menerima perutusan turun ke dunia demi keselamatan umat manusia. Dengan demikian partisipasi dalam politik demi terwujudnya hidup lebih baik, adalah panggilan hidup seluruh umat Kristiani tanpa kecuali. Hanya, politik disini harus dimengerti secara luas dalam rangka perwujudan kebaikan umum, bukan hanya dalam arti sempit politik praktis menjadi anggota partai, legistatif, eksekutif, dll, semata. Terlibat politik (dalam arti luas) demi kebaikan umum juga merupakan kewajiban setiap warganegara. Dengan demikian keterlibatan politik sekaligus merupakan perwujudan slogan: “100 % Katolik dan 100% Indonesia”, atau “pro ecclesia et patria” (untuk Gereja dan negara).
Kalau keterlibatan politik secara luas bagi umat katolik dipahami sebagai panggilan iman, maka dasar yang digunakan juga harus dalam rangka pewartaan ajaran iman itu sendiri, tidak boleh lain. Berpolitik berarti membawa nilai-nilai ajaran iman kedalam dunia nyata, masyarakat negara. Lalu bagaimana caranya? Ada 2 kegiatan politik yang khas dalam sistem demokrasi yang menuntut partisipasi aktif warga negara, yaitu: 1. Pemilihan, dan 2. Masa mengawal antar pemilihan. Berikut tips sederhana bagi keduanya:
Pemilihan
Termasuk disini adalah pemilihan pemimpin eksekutif (presiden, gubernur, walikota, dll), partai, wakil rakyat (DPR, DPRD, dst). Memilih pemimpin atau partai berarti memilih yang paling memungkinkan membawa perubahan kearah kebaikan atau mengimplementasikan nilai-nilai ajaran iman. Nilai-nilai ajaran iman Katolik telah diringkas menjadi 8 (delapan) nilai etika politik yaitu: kebaikan hati, keberpihakan pada kehidupan, kesejahteraan umum, subsidiaritas, solidaritas, hak-hak asasi manusia, penolakan terhadap kekerasan, dan persaudaraan semesta.[1][1] Franz Magnis Suseno, Katolik Itu Apa?, Kanisius, Yogyakarta, 2017, hal 184-185.
Karena itu tidak perlu memilih berdasarkan fokus: agama, etnis, kedekatan pribadi, atau malah kepentingan/keuntungan diri. Tetapi pilihlah yang paling memungkinkan nilai-nilai ajaran iman itu diwujudkan secara maksimal. Tentunya kader politik Katolik yang berkualitas memenuhi kriteria ini. Tetapi kader yang beragama lain pun, dengan kualitas yg baik, memungkinkan perwujudan nilai-nilai universal ini. Para tokoh bangsa telah membuktikan hal ini.
Memilih yang baik adalah panggilan iman Kristiani! Untuk itu memang diperlukan kejelian untuk membaca situasi dan sepak terjang calon di masa lalu (track record). Perlu juga mendapat gambaran tentang orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada disekitar mereka. Pemimpin yang hidup disekitar “penyamun” cenderung menjadi “pemimpin penyamun”, dan sebaliknya. Ada kontrak-kontrak politik yang melekat dalam kegiatan politik. Dengan demikian keterlibatan aktif untuk mencari informasi yang sesuai memang sangat dibutuhkan. Membaca berita politik dan perkembangan negara juga sangat membantu. Berdiskusi mendalami kedelapan nilai etika politik Katolik bersama kelompok-kelompok, dengan para gembala, narasumber yang kompeten dll, tentu sangat membantu dan perlu.
Memang tidak mungkin menemukan partai atau pribadi yang 100 % sempurna atau karakternya mewakili kedelapan nilai itu secara utuh. Tidak ada manusia yang sempurna, juga kita semua. Karena itu tidak berlebihan apabila Romo Magnis menyatakan: “pemilu bukan untuk memilih yang terbaik tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa”. Setidaknya, pilihlah yang paling memungkinkan nilai-nilai keutamaan Kristiani itu diimplementasikan secara maksimal.
Mengawal masa antar pemilihan
Ini sebenarnya adalah bagian terpenting yang membutuhkan partisipasi aktif warga negara dalam sistem demokrasi. Namun sayangnya, kebanyakan masyarakat masih menganggap partisipasi politik hanya terbatas saat pemilihan. Ini salah kaprah! Sehabis pemilihan mereka lepas tangan, bersikap masa bodoh, dan baru kembali aktif lagi saat pemilihan berikutnya. Padahal pemimpin bisa berubah, janji bisa dilupakan, apalagi ditengah tekanan-tekanan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan demi kepentingan diri. Pemahaman yang salah tentang masa antar pemilihan sering dimanfaatkan para politikus “nakal” dengan mengumbar janji-janji yang fantastis saat kampanye, tanpa didukung komitmen atas implementasinya. Politik menjadi sekadar alat untuk mendapatkan kursi belaka.
Masa diantara pemilu ke pemilu selanjutnya, merupakan masa untuk “mengawal” arah kepemimpinan menuju yang dicita-citakan bersama. Ada banyak cara konstitusional yang dapat ditempuh untuk menyampaikan pendapat/masukan dalam masa ini, bisa lewat ruang publik, pejabat, wakil rakyat, partai, petisi, surat terbuka, bahkan juga bisa lewat unjuk rasa, dll. Lalu apa yang harus dikawal?
Ada beberapa kriteria dasar yang digunakan dalam Gereja Katolik untuk menilai keberhasilan sebuah kepemimpinan politik sesuai nilai-nilai Kristiani. Salah satunya adalah kriteria: keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan (justice, peace, and intergration of creation, atau sering disingkat JPIC). Kepemimpinan yang baik seharusnya menciptakan tatanan masyarakat yang makin adil, makin damai, dan makin memelihara keutuhan semua ciptaan (alam semesta) dengan baik. Sebaliknya, kepemimpinan yang buruk membawa pada arah maraknya ketidakadilan, konflik, dan kehancuran lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran politik masyarakat pada masa lalu telah mewariskan permasalahan serius dalam ketiga kriteria itu. Ketiga kriteria ini dan 8 etika politik Kristiani ternyata juga sangat cocok dengan nilai-nilai dasar negara kita: Pancasila. Silahkan direnungkan……. Dengan demikian, mengamalkan Pancasila, menjaga NKRI sesuai amanah Pancasila, adalah selaras dengan melaksanakan panggilan iman Kristiani.
Akhir kata, dari pembahasan sederhana sebelumnya nampak bahwa kewajiban iman dan kewajiban warganegara itu selaras, setujuan. Melaksanakan ajaran iman dengan baik juga sekaligus berproses menjadi warganegara yang baik. Berjuang menyelamatkan negeri tercinta juga sekaligus berjuang menyelamatkan diri sendiri dalam iman. Mengupayakan yang terbaik untuk semua yang diluar sekaligus juga upaya mencapai tujuan kekudusan diri. Lalu kalau ini sungguh panggilan yang mulia dan menyelamatkan, mengapa kita tidak dengan serius memulainya sekarang untuk terlibat dengan segenap talenta kita?
Penulis adalah Dewan Pakar Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) DPC Palembang