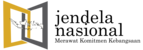Oleh: Edi Danggur, SH, MM, MH
Jelang Pilgub NTT Juni 2018, moralitas pribadi seorang calon gubernur (cagub) diumbar ke ruang publik. Seolah-olah tidak ada lagi ranah privat dalam diri si cagub tidak ada lagi. Sebab dugaan hubungan seksual si cagub dengan seorang wanita dewasa telah diobok-obok di berbagai media sosial.
Apakah dugaan adanya hubungan seksual antara si cagub dengan wanita dewasa dimaksud merupakan isu hukum yang patut diobral ke ruang publik?
Kaidah Kesusilaan
Di tengah masyarakat ada beberapa tata kaidah sosial. Para ahli hukum memperkenalkan dua kelompok tata kaidah sosial, yaitu:
Pertama, kaidah dengan aspek kehidupan antarpribadi. Di dalamnya ada kaidah sopan santun atau adat istiadat dan kaidah hukum.
Kedua, kaidah dengan aspek kehidupan pribadi. Di dalamnya ada kaidah kepercayaan atau keagamaan dan kaidah kesusilaan (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1978:6; Sudikno Mertokusumo, 2014:7).
Kalau kita hendak menilai moralitas pribadi seseorang, termasuk dugaan hubungan seksual antara seorang cagub dengan wanita dewasa tersebut, hal itu ada dalam ranah kaidah kesusilaan. Jika demikian maka masalah moralitas pribadi cagub itu bukan isu hukum. Mengapa?
Sebab kaidah kesusilaan itu berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir.
Berhubung moralitas pribadi ini menyangkut kehidupan pribadi maka yang mengontrol bukan sesuatu yang berasal dari luar tetapi berasal dari nurani individual si cagub. Kegelisahan diri yang hanya dirasakan oleh individu si cagub, itulah yang mengontrol dari dalam.
Itu sebabnya kaidah kesusilaan ini berasal dari dalam manusia itu sendiri, bersifat otonom, yang berisi kewajiban-kewajiban semata, yang tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia.
Batin manusia itu sendiri yang mengancam memberikan sanksi kepada orang tersebut dalam wujud: rasa salah, rasa malu, rasa takut atau batin yang gelisah.
Tidak ada hukum atau kekuasaan apa pun dari luar diri si cagub yang bisa menghukumnya jika si cagub diduga melanggar kaidah kesusilaan itu. Ini sesuai dengan adagium universal: “cogitationis poenam nemo patitur” – tidak seorang pun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan atau yang ada di batinnya (Henry Campbell Black, 1990:259).
Mau Sama Mau
Itu sebabnya para pembuat undang-undang di berbagai negara memasukkan pelanggaran kaidah kesusilaan ini sebagai delik aduan. Artinya, otonomi ada pada kedua belah pihak atau orang-orang yang berkepentingan dugaan seksual itu dilaporkan atau tidak kehadapan aparat penegak hukum.
Kalau dilaporkan, maka baru ada kualifikasi tindak pidana zinah. Artinya sudah masuk ranah hukum. Tetapi selagi para pihak atau keluarganya tidak membawa masalah ini ke hadapan aparat penegak hukum maka dugaan hubungan seksual dimaksud tetap bukan merupakan isu hukum.
Dalam kasus si cagub, tentu saja si cagub dan si wanita tidak akan melaporkan soal ini ke aparat penegak hukum. Sebab keduanya sudah sama-sama dewasa dan keduanya melakukan hubungan seksual atas dasar “suka sama suka”. Sehingga tidak ada ketidakadilan, tidak ada pelecehan atau tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh satu oranh terhadap yang lain. Maka dalam hubungan seksual seperti ini berlaku adagium ini: “volenti non fit injuria” – pada orang yang (melakukan hubungan seksual) atas dasar suka sama suka atau mau sama mau, tidak ada ketidakadilan dan tidak ada pelecehan (Th. L. Verhoeven & Philipus Djuang, 2010:72).
Dengan argumentasi di atas maka dapat dimengerti bahwa hubungan seksual antara si cagub dan si wanita dewasa itu bukan sebuah kejahatan. Sehingga hukum dan penegak hukum pun tidak dapat menjangkau ke ruang privat keduanya.
Si cagub memang pejabat publik. Tetapi mengobok-obok ranah privasi pejabat juga adalah sebuah pelanggaran HAM.
Tidak ada kekuasan di luar dirinya yang bisa memaksanya menanggalkan jabatannya atau mundur dari pencalonan untuk meraih jabatan publik yang lebih tinggi. Hanya batin si cagub yang bisa mengadili semua tindakannya yang dilakukannya dalam ruang privat.
Jangan Mengobral Kemunafikan
Jika tidak ada isu hukum dalam hubungan seksual antara si cagub dan si wanita, apakah mengobral isu ini ke ruang publik sebagai kampanye bahwa cagub-cagub lainnya mempunyai moralitas pribadi yang lebih baik?
Chin Ning Chu, seorang mantan biarawati katolik yang kini menjadi salah satu konsultan bisnis dan politik terkemuka di AS, dalam bukunya berjudul _Thick Face Black Heart,_mengatakan:
“Saat ini, warga yang ‘paling suci’ dengan maksud yang paling benar, berupaya keras untuk memaksakan standard dan kode moral mereka sehubungan dengan masalah-masalah sosial kepada warganya yang lain atas nama ‘kebaikan dan kesopanan’. Pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah: bisakah kita begitu meyakini bahwa konsep kita mengenai kebajikan bukan malah menjadi kekuatan yang memaksakan terciptanya kebencian, ketidakpedulian dan kemunafikan? Bukankah kita, sekali lagi, tengah menydutkan kemanusiaan?” (1997:351).
Chin Ning Chu benar, penampilan lahiriah seseorang tidak serta-merta ia orang baik. Orang yang datang kebaktian atau misa tiap pagi hari atau paling tidak tiap hari minggu ke gereja atau tiap minggu, duduk paling depan pula, tidak serta-merta ia mempunyai moralitas yang lebih baik.
Pejabat publik yang kadang merampas mimbar pimpinan agama untuk berkotbah dalam setiap upacara keagamaan, tidak serta-merta para pejabat itu dicap berperilaku bagus dan bermoral bagus.
Itu sebabnya kaum bijak menasehati: “habitus non facit monachum” – jangan karena seseorang berbaju putih panjang, lantas kau katakan bahwa itu orang suci atau seorang rahib. Begitu pula ada adagium ini: “barba non facit philosophum” – jangan hanya karena orang itu berjanggut, lantas orang itu serta-merta kau anggap ia seorang filsuf.
Mengapa? Sebab penampilan fisik tidak selamanya sejalan atau tidak mencerminkan keadaan rohani orang itu sebenarnya. Ya, memang manusia hanya melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati.
Penulis adalah Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.